Di luar krisis Myanmar yang belum berakhir sepenuhnya, ASEAN masih menghadapi ujian oleh konflik bersenjata Kamboja–Thailand yang terus berulang dan tak kunjung berdamai. Konflik ini bukan sekadar perselisihan bilateral, melainkan cermin rapuhnya tata kelola keamanan kawasan Asia Tenggara. Bagi ASEAN yang sejak awal didesain sebagai komunitas perdamaian, kegagalan menghentikan eskalasi konflik antaranggota menjadi alarm serius tentang relevansi dan efektivitasnya di tengah dinamika geopolitik global yang kian keras.
Sejumlah upaya diplomatik telah ditempuh. Pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada 22 Desember 2025, disusul dialog militer tiga hari di perbatasan Chanthaburi, serta pertemuan sela KTT ASEAN yang bahkan dihadiri Presiden AS Donald Trump, menunjukkan intensitas perhatian internasional. Namun, fakta bahwa jet tempur F-15 Thailand tetap menyerang wilayah Kamboja saat para menlu bersidang, menegaskan bahwa diplomasi ASEAN gagal menciptakan efek penahan (deterrent diplomacy).
Dari perspektif realisme struktural, kegagalan ini dapat dipahami sebagai lemahnya institusi regional dalam sistem internasional yang anarkis. Negara tetap menjadi aktor utama yang memprioritaskan keamanan dan kedaulatan. Ketika konflik menyentuh wilayah dan harga diri nasional, seperti pada sengketa Kamboja–Thailand, norma regional dengan mudah tersingkir oleh kalkulasi kekuatan militer dan politik domestik masing-masing negara.
Pendekatan realisme saja tidak cukup menjelaskan mengapa ASEAN terlihat kehilangan wibawa. Di sinilah liberal institusionalisme memberi perspektif tambahan. Institusi regional hanya efektif bila negara anggota bersedia menyerahkan sebagian ruang diskresi kebijakan demi kepentingan kolektif. Prinsip nonintervensi ASEAN, yang selama ini dianggap fondasi stabilitas, justru menjadi penghambat utama resolusi konflik ketika solidaritas regional dibutuhkan.
Malaysia sebagai ketua bergilir ASEAN 2025 telah menjalankan peran mediasi semaksimal mungkin. Namun, seperti pengalaman penanganan krisis Myanmar sejak 2021, ketua bergilir tidak pernah cukup kuat bertindak sendirian. ASEAN sejak awal tidak dirancang dengan mekanisme kepemimpinan tunggal yang kuat, melainkan bertumpu pada kepemimpinan kolektif, yang dalam praktiknya sering berujung pada kebuntuan.
Dalam konteks inilah, Indonesia seharusnya tampil lebih aktif. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengamanatkan peran dalam “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Mandat normatif ini bukan slogan kosong, melainkan fondasi etis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Sejarah mencatat konsistensi Indonesia sebagai juru damai kawasan. Dari peran Mochtar Kusumaatmadja dalam krisis Kamboja pasca-invasi Vietnam, Jakarta Informal Meeting (JIM) yang diprakarsai Ali Alatas untuk menyelesaikan konflik Kamboja pada 1988–1991, mediasi konflik Kamboja–Thailand 2011 oleh Marty Natalegawa, hingga peran Retno Marsudi dalam krisis Myanmar 2021, Indonesia memiliki modal diplomatik yang belum dimiliki negara ASEAN lain.
Lebih jauh, pengalaman panjang Indonesia memediasi konflik Filipina–Moro National Liberation Front (MNLF) selama hampir empat dekade menunjukkan kapasitas Indonesia dalam conflict transformation, bukan sekadar conflict management. Indonesia tidak hanya memfasilitasi perjanjian damai, tetapi juga terlibat sebagai pengawas implementasi dan pengirim tim pemantau di lapangan.
Secara teoritis, posisi Indonesia sering dipahami sebagai middle power dengan peran norm entrepreneur. Indonesia bukan kekuatan besar, tetapi memiliki legitimasi moral, jejaring diplomatik, dan rekam jejak yang memungkinkan pembentukan norma regional. Inilah basis asumsi Indonesia sebagai natural leader ASEAN, yang lahir dari kombinasi ukuran, stabilitas, dan diplomasi moderat.
Namun, status natural leader itu kini dipertanyakan. Diplomasi Indonesia terlihat kurang aktif di internal ASEAN, meski Presiden Prabowo Subianto cukup aktif dalam diplomasi global. Dari sudut pandang role theory dalam hubungan internasional, terdapat kesenjangan antara peran yang diharapkan komunitas regional terhadap Indonesia dan peran yang benar-benar dijalankan saat ini.
Ketidakaktifan Indonesia memperparah krisis kepemimpinan ASEAN. Hampir semua negara anggota menghadapi konflik internal atau eksternal, sementara ASEAN gagal mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang efektif. Dalam istilah institutional decay, ASEAN mengalami erosi kapasitas akibat ketergantungan berlebihan pada konsensus dan absennya aktor penggerak utama.
Kondisi ini membuka ruang masuknya kekuatan besar. Amerika Serikat mengancam tarif terhadap Kamboja dan Thailand, sementara China mengirim diplomatnya untuk melakukan shuttle diplomacy. Dari perspektif teori rivalitas kekuatan besar, lemahnya otonomi strategis ASEAN menjadikannya arena kontestasi eksternal yang berisiko tinggi bagi stabilitas kawasan.
Konflik Kamboja–Thailand juga perlu dibaca melalui teori konflik kedaulatan. Sengketa teritorial yang bersumber pada tafsir sejarah berbeda, mirip dengan konflik Laut China Selatan, hampir selalu bersifat zero-sum. Isu ini tidak mudah dikompromikan karena menyentuh identitas nasional dan legitimasi politik domestik masing-masing negara.
Dalam konteks seperti ini, pendekatan komunikasi diplomasi modern menjadi krusial. Diplomasi tidak lagi cukup bersifat elitis dan tertutup, tetapi harus mengelola persepsi publik, narasi sejarah, dan sensitivitas identitas. Indonesia memiliki keunggulan dalam track 1.5 dan track 2 diplomacy, memanfaatkan jejaring militer, intelijen, akademisi, dan masyarakat sipil di kedua negara.
Modal sosial Indonesia di Kamboja dan Thailand sangat besar. Militer kedua negara memiliki sejarah panjang kerja sama dengan TNI, begitu pula jejaring intelijen. Di Kamboja, peran Indonesia dalam mengakhiri perang saudara masih hidup dalam ingatan kolektif elite politik. Modal inilah yang seharusnya diaktivasi kembali secara strategis.
Sebagai middle power, Indonesia tidak perlu memihak satu pihak. Justru kekuatannya terletak pada kemampuan menjadi honest broker yang dipercaya. Melalui diplomasi aktif, mekanisme pencegahan konflik, dan inisiatif pembentukan norma penyelesaian sengketa damai, Indonesia dapat mengembalikan fungsi ASEAN sebagai penjaga stabilitas kawasan.
Kegagalan menangani konflik Kamboja–Thailand bukan hanya soal satu konflik bilateral, tetapi soal masa depan ASEAN itu sendiri. Jika ASEAN tidak mampu mengelola konflik internal, maka klaimnya sebagai komunitas keamanan regional akan kehilangan legitimasi, dan ketergantungan pada aktor eksternal akan semakin dalam.
Pada akhirnya, konflik Kamboja–Thailand adalah ujian kepemimpinan regional Indonesia. Dengan menggabungkan teori hubungan internasional modern, pemahaman konflik kedaulatan, dan komunikasi diplomasi kontemporer, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk kembali menjadi inisiator problem solving di ASEAN. Pertanyaannya bukan pada kapasitas, melainkan pada kemauan politik untuk kembali memimpin dari depan, bukan sekadar hadir sebagai penonton di kawasan sendiri.

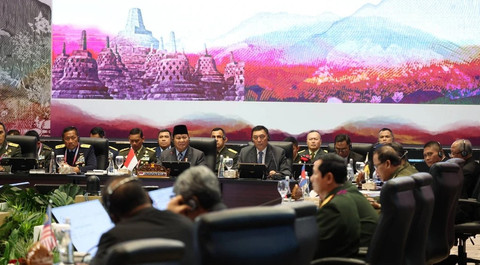




:strip_icc()/kly-media-production/medias/5341961/original/082581700_1757342936-Timnas_Indonesia_vs_Lebanon_-13.jpg)
