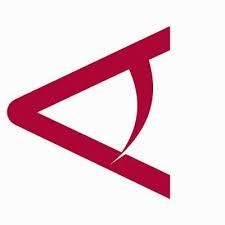Jakarta (ANTARA) - Indonesia sering dipuji sebagai bangsa yang religius. CEOWORLD Magazine pada 2024 menempatkan Indonesia di posisi ketujuh negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia.
Di ruang publik, masyarakat terbiasa menyebut nama Tuhan dan agama untuk merespons segala macam persoalan. Rumah ibadah berdiri megah, kegiatan keagamaan berlangsung semarak, dan kehidupan sosial penuh dengan simbol-simbol religius.
Sayangnya, di tengah wajah religius itu, masih kerap terjadi fenomena fanatisme sempit, intoleransi, kecurigaan berlebihan, hingga perilaku yang tidak selaras dengan nilai kasih, keadilan, dan kejujuran.
Di sinilah paradoks keberagamaan muncul, ketika Tuhan diagungkan melalui ritual dan kata, tetapi kerap diabaikan dalam wajah nyata relasi antarmanusia.
Dalam keberagamaan, ajakan beribadah atau berdakwah memang baik, tetapi keyakinan yang dewasa senantiasa disertai kesadaran bahwa keputusan akhir berada di tangan Tuhan. Keikhlasan seperti ini dapat menepis dorongan untuk memaksakan keyakinan pribadi.
Data Setara Institute pada 2024 menunjukkan bahwa sejumlah kota di Indonesia masih berada pada kategori intoleransi yang memerlukan perhatian.
Fenomena intoleransi tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka. Tetapi sering tampil sebagai cibiran halus di media sosial, pelabelan negatif, atau kecurigaan yang terus dipelihara.
Fenomena ini ibarat api dalam sekam yang kecil, nyaris tak terlihat, tetapi berpotensi memanaskan ruang sosial bila dibiarkan. Menariknya, sebagian pelaku intoleransi justru tampil religius secara lahiriah.
Ritual berjalan, doa terucap, tetapi nilai ilahi belum sepenuhnya mewujud dalam sikap hormat terhadap martabat sesama.
Keberagamaan yang matang sesungguhnya melahirkan ketenangan batin. Keyakinan bahwa Tuhan Mahakuasa dan Mahatahu seharusnya menumbuhkan rasa percaya, bukan ketakutan berlebihan terhadap perbedaan.
Menumbuhkan keberagaman
Di banyak ruang, rasa takut justru mendorong lahirnya klaim kebenaran yang ingin dipaksakan. Di titik ini, ego sering menyamar sebagai iman.
Ketika ajaran agama dipersempit hanya dalam kerangka idealisme kelompok, Tuhan yang Mahabesar seolah ditarik turun ke ruang sempit kepentingan manusia.
Padahal, inti ajaran agama-agama besar selalu menekankan kasih, keadilan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Ruang digital di Indonesia kini menjadi panggung terbuka bagi kedua wajah keberagamaan itu. Di satu sisi, media sosial mempercepat penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan stigmatisasi berbasis identitas.
Di sisi lain, ruang digital juga melahirkan inisiatif dialog lintas iman, edukasi toleransi, serta gerakan solidaritas yang menyejukkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki energi sosial yang besar untuk menumbuhkan keberagamaan yang lebih dewasa dan mencerahkan.
Satu hal yang patut diingat, setiap agama memiliki pemeluk yang baik dan yang sebaliknya. Tidak ada satu pun agama yang seluruh pengikutnya sempurna.
Bila ada seseorang yang jujur, adil, rendah hati, dan penuh kasih, itu tidak semata lahir dari label agama, melainkan dari kesadaran batin yang selaras dengan nilai ilahi.
Begitu pula sebaliknya, perilaku koruptif, intoleran, atau penuh kebencian bukan pantulan ajaran Tuhan, melainkan pantulan ego manusia.
Pilihan beragama atau berpindah agama pada orang dewasa biasanya merupakan perjalanan batin yang sangat personal. Keputusan itu kerap lahir dari proses refleksi panjang dan sentuhan hati.
Menghadirkan Tuhan
Menyederhanakan proses spiritual tersebut hanya sebagai hasil bujukan manusia justru berisiko merendahkan otoritas Tuhan yang diyakini sebagai sumber kehidupan.
Karena itu, menghadirkan kembali Tuhan sebagai realitas yang hidup menjadi sangat penting. Keteraturan alam, keajaiban tubuh manusia, dan harmoni ciptaan menunjukkan adanya desain dan kehendak yang agung.
Kesadaran ini, ketika tumbuh dengan tulus, memindahkan pusat hidup dari ego menuju kasih. Rasa takut berlebihan mereda, kejujuran mendapatkan tempat, dan keadilan menjadi panggilan nurani.
Dalam relasi sosial, tumbuh penghormatan pada martabat setiap manusia sebagai ciptaan yang mulia.
Dalam konteks Indonesia yang tengah bergerak cepat, dari transformasi digital, dinamika ekonomi, hingga perubahan sosial, agama semestinya hadir sebagai sumber energi moral yang menyejukkan ruang bersama.
Keberagamaan yang matang akan melahirkan warga bangsa yang bijak, tangguh, dan saling menghormati.
Keberagamaan semacam ini tidak mudah terprovokasi, tidak cepat curiga, dan tidak mudah memusuhi perbedaan, karena yakin bahwa Tuhan tidak pernah kalah oleh keragaman.
Pada akhirnya, refleksi menjadi bagian penting dari perjalanan iman. Tiga pertanyaan sederhana mungkin dapat membuka kesadaran batin.
Apakah pusat hidup berada pada ego pribadi atau pada kehadiran Tuhan? Apakah laku hidup sudah mencerminkan integritas, atau masih menyisakan kemunafikan yang tersembunyi? Dan yang paling mendasar, apakah keyakinan kepada Tuhan sungguh tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya menentukan apakah religiusitas hanya berhenti pada simbol, atau benar-benar menjadi cahaya yang menerangi kehidupan bersama.
Di titik ini, pendidikan toleransi menjadi sangat penting, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Literasi keberagamaan perlu diarahkan pada pemahaman yang utuh bahwa iman tidak lahir dari rasa takut pada yang berbeda, melainkan dari penghormatan pada martabat manusia.
Dialog lintas iman, kerja sama sosial antar-komunitas, serta pembiasaan bertemu dan bekerja bersama dalam ruang publik dapat menjadi jalan sederhana untuk merawat kepercayaan.
Ketika orang bertemu langsung, prasangka biasanya melebur. Hal yang tersisa bukan lagi label agama, tetapi kemanusiaan yang sama-sama ingin hidup damai, sejahtera, dan bermakna.
Dengan cara ini, keberagamaan tidak berhenti sebagai identitas, melainkan tumbuh sebagai kekuatan moral yang membangun masa depan Indonesia.
*) A Roni Kurniawan adalah praktisi pendidikan dan pengembang metode edukasi praktis berbasis psikologi pada Rumah Belajar Bersama (Rbebe)
Di ruang publik, masyarakat terbiasa menyebut nama Tuhan dan agama untuk merespons segala macam persoalan. Rumah ibadah berdiri megah, kegiatan keagamaan berlangsung semarak, dan kehidupan sosial penuh dengan simbol-simbol religius.
Sayangnya, di tengah wajah religius itu, masih kerap terjadi fenomena fanatisme sempit, intoleransi, kecurigaan berlebihan, hingga perilaku yang tidak selaras dengan nilai kasih, keadilan, dan kejujuran.
Di sinilah paradoks keberagamaan muncul, ketika Tuhan diagungkan melalui ritual dan kata, tetapi kerap diabaikan dalam wajah nyata relasi antarmanusia.
Dalam keberagamaan, ajakan beribadah atau berdakwah memang baik, tetapi keyakinan yang dewasa senantiasa disertai kesadaran bahwa keputusan akhir berada di tangan Tuhan. Keikhlasan seperti ini dapat menepis dorongan untuk memaksakan keyakinan pribadi.
Data Setara Institute pada 2024 menunjukkan bahwa sejumlah kota di Indonesia masih berada pada kategori intoleransi yang memerlukan perhatian.
Fenomena intoleransi tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka. Tetapi sering tampil sebagai cibiran halus di media sosial, pelabelan negatif, atau kecurigaan yang terus dipelihara.
Fenomena ini ibarat api dalam sekam yang kecil, nyaris tak terlihat, tetapi berpotensi memanaskan ruang sosial bila dibiarkan. Menariknya, sebagian pelaku intoleransi justru tampil religius secara lahiriah.
Ritual berjalan, doa terucap, tetapi nilai ilahi belum sepenuhnya mewujud dalam sikap hormat terhadap martabat sesama.
Keberagamaan yang matang sesungguhnya melahirkan ketenangan batin. Keyakinan bahwa Tuhan Mahakuasa dan Mahatahu seharusnya menumbuhkan rasa percaya, bukan ketakutan berlebihan terhadap perbedaan.
Menumbuhkan keberagaman
Di banyak ruang, rasa takut justru mendorong lahirnya klaim kebenaran yang ingin dipaksakan. Di titik ini, ego sering menyamar sebagai iman.
Ketika ajaran agama dipersempit hanya dalam kerangka idealisme kelompok, Tuhan yang Mahabesar seolah ditarik turun ke ruang sempit kepentingan manusia.
Padahal, inti ajaran agama-agama besar selalu menekankan kasih, keadilan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Ruang digital di Indonesia kini menjadi panggung terbuka bagi kedua wajah keberagamaan itu. Di satu sisi, media sosial mempercepat penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan stigmatisasi berbasis identitas.
Di sisi lain, ruang digital juga melahirkan inisiatif dialog lintas iman, edukasi toleransi, serta gerakan solidaritas yang menyejukkan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki energi sosial yang besar untuk menumbuhkan keberagamaan yang lebih dewasa dan mencerahkan.
Satu hal yang patut diingat, setiap agama memiliki pemeluk yang baik dan yang sebaliknya. Tidak ada satu pun agama yang seluruh pengikutnya sempurna.
Bila ada seseorang yang jujur, adil, rendah hati, dan penuh kasih, itu tidak semata lahir dari label agama, melainkan dari kesadaran batin yang selaras dengan nilai ilahi.
Begitu pula sebaliknya, perilaku koruptif, intoleran, atau penuh kebencian bukan pantulan ajaran Tuhan, melainkan pantulan ego manusia.
Pilihan beragama atau berpindah agama pada orang dewasa biasanya merupakan perjalanan batin yang sangat personal. Keputusan itu kerap lahir dari proses refleksi panjang dan sentuhan hati.
Menghadirkan Tuhan
Menyederhanakan proses spiritual tersebut hanya sebagai hasil bujukan manusia justru berisiko merendahkan otoritas Tuhan yang diyakini sebagai sumber kehidupan.
Karena itu, menghadirkan kembali Tuhan sebagai realitas yang hidup menjadi sangat penting. Keteraturan alam, keajaiban tubuh manusia, dan harmoni ciptaan menunjukkan adanya desain dan kehendak yang agung.
Kesadaran ini, ketika tumbuh dengan tulus, memindahkan pusat hidup dari ego menuju kasih. Rasa takut berlebihan mereda, kejujuran mendapatkan tempat, dan keadilan menjadi panggilan nurani.
Dalam relasi sosial, tumbuh penghormatan pada martabat setiap manusia sebagai ciptaan yang mulia.
Dalam konteks Indonesia yang tengah bergerak cepat, dari transformasi digital, dinamika ekonomi, hingga perubahan sosial, agama semestinya hadir sebagai sumber energi moral yang menyejukkan ruang bersama.
Keberagamaan yang matang akan melahirkan warga bangsa yang bijak, tangguh, dan saling menghormati.
Keberagamaan semacam ini tidak mudah terprovokasi, tidak cepat curiga, dan tidak mudah memusuhi perbedaan, karena yakin bahwa Tuhan tidak pernah kalah oleh keragaman.
Pada akhirnya, refleksi menjadi bagian penting dari perjalanan iman. Tiga pertanyaan sederhana mungkin dapat membuka kesadaran batin.
Apakah pusat hidup berada pada ego pribadi atau pada kehadiran Tuhan? Apakah laku hidup sudah mencerminkan integritas, atau masih menyisakan kemunafikan yang tersembunyi? Dan yang paling mendasar, apakah keyakinan kepada Tuhan sungguh tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya menentukan apakah religiusitas hanya berhenti pada simbol, atau benar-benar menjadi cahaya yang menerangi kehidupan bersama.
Di titik ini, pendidikan toleransi menjadi sangat penting, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Literasi keberagamaan perlu diarahkan pada pemahaman yang utuh bahwa iman tidak lahir dari rasa takut pada yang berbeda, melainkan dari penghormatan pada martabat manusia.
Dialog lintas iman, kerja sama sosial antar-komunitas, serta pembiasaan bertemu dan bekerja bersama dalam ruang publik dapat menjadi jalan sederhana untuk merawat kepercayaan.
Ketika orang bertemu langsung, prasangka biasanya melebur. Hal yang tersisa bukan lagi label agama, tetapi kemanusiaan yang sama-sama ingin hidup damai, sejahtera, dan bermakna.
Dengan cara ini, keberagamaan tidak berhenti sebagai identitas, melainkan tumbuh sebagai kekuatan moral yang membangun masa depan Indonesia.
*) A Roni Kurniawan adalah praktisi pendidikan dan pengembang metode edukasi praktis berbasis psikologi pada Rumah Belajar Bersama (Rbebe)