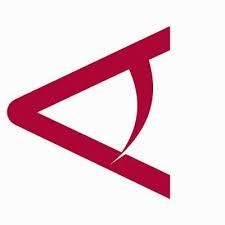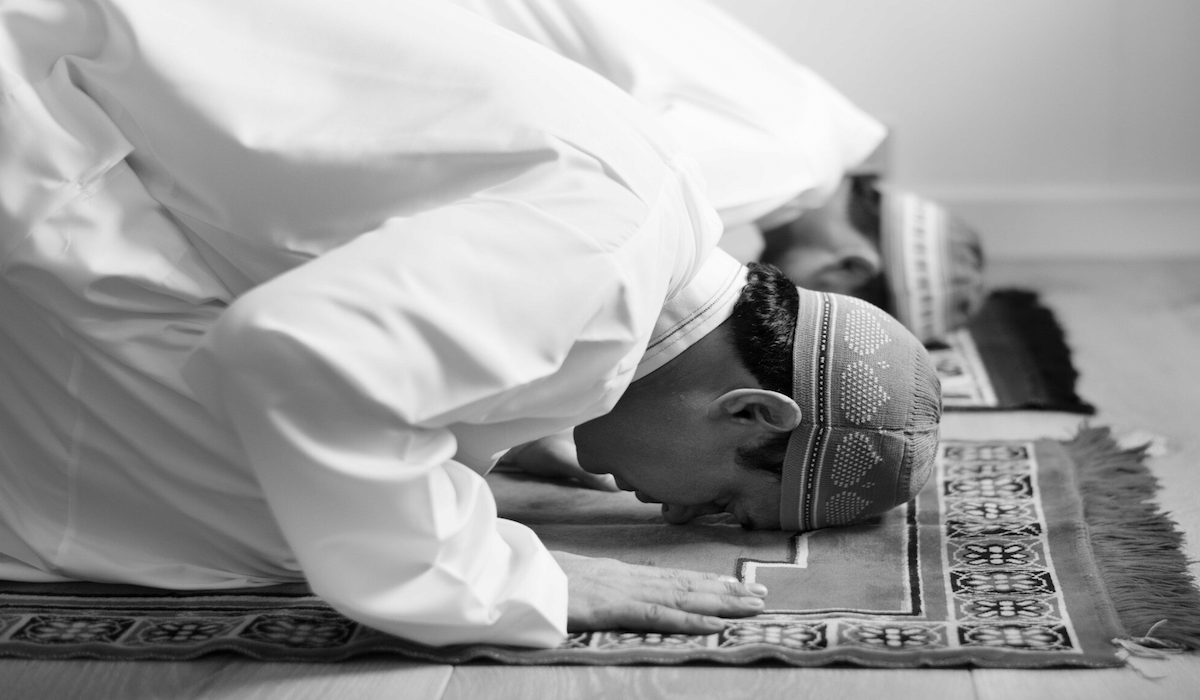Jakarta (ANTARA) - Lonjakan harga kakao dunia hingga menembus rekor 11.000 dolas AS (sekitar Rp176 juta) per ton pada 2023 semestinya menjadi angin segar bagi negara produsen seperti Indonesia.
Kenaikan harga akibat anjloknya pasokan dari Afrika membuka peluang besar untuk mendongkrak pendapatan petani sekaligus memperkuat devisa ekspor. Namun realitas di lapangan justru berkebalikan.
Di tengah posisinya sebagai salah satu eksportir produk olahan kakao terbesar dunia, Indonesia malah bergantung pada impor biji kakao mentah untuk menggerakkan industrinya sendiri.
Paradoks pun mengemuka, pabrik pengolahan tumbuh pesat dan produknya laku keras di pasar global, sementara sektor hulu melemah dan semakin bergantung pada pasokan luar negeri.
Padahal, Indonesia pernah berjaya di panggung kakao dunia. Pada 2010, produksi nasional mencapai puncaknya sekitar 844 ribu ton dan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga produsen kakao global.
Namun sejak itu tren berbalik arah. Produksi kakao terus merosot hingga hanya sekitar 632 ribu ton pada 2023 seiring menyusutnya luas kebun dari 1,56 juta hektare menjadi 1,39 juta hektare dalam kurun empat tahun. Penurunan ini terjadi justru saat permintaan global cokelat terus meningkat.
Ironinya, di tengah produksi biji kakao yang stagnan, industri pengolahan dalam negeri justru melaju kencang. Ekspor produk olahan kakao Indonesia telah menembus ratusan ribu ton dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar AS (setara Rp16 triliun), menjadikan Indonesia eksportir cocoa butter terbesar kedua dunia.
Hilirisasi tampak sukses di atas kertas, tetapi fondasinya rapuh karena pasokan bahan baku lokal tak mencukupi.
Kesenjangan antara kapasitas industri dan produksi kebun menciptakan tekanan serius pada pasokan kakao nasional. Kebutuhan bahan baku industri domestik diperkirakan mendekati 400 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri tak mampu mengimbangi. Kekurangan ini ditutup dengan impor yang terus meningkat, bahkan mencapai ratusan ribu ton dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar berasal dari Ekuador.
Akibatnya, kapasitas terpasang pabrik yang mencapai sekitar 700 ribu ton per tahun baru dimanfaatkan sebagian. Indonesia menjadi eksportir besar kakao olahan, tetapi nilai tambah dari hilirisasi belum sepenuhnya dinikmati petani lokal.
Mutu biji lokal vs kebutuhan industri
Salah satu akar persoalan kakao nasional terletak pada mutu biji kakao lokal yang belum konsisten memenuhi standar industri. Dalam industri cokelat, fermentasi merupakan tahap krusial untuk membentuk cita rasa dan kualitas kimia biji kakao. Namun di tingkat petani, praktik fermentasi masih sangat terbatas.
Mayoritas petani menjual biji kakao kering tanpa fermentasi dengan harga lebih rendah, sementara biji kakao yang difermentasi dengan baik memiliki nilai jual lebih tinggi. Keterbatasan pengetahuan, sarana, dan pendampingan membuat proses fermentasi sering tidak optimal.
Industri pun kerap mengeluhkan kadar asam yang tinggi dan rasa yang tidak seragam meskipun standar nasional (SNI 2323:2008) telah mewajibkan fermentasi sebagai syarat mutu. Tanpa dukungan teknis yang memadai, standar tersebut sulit diterapkan secara luas di lapangan.
Kendala mutu ini membuat pabrik pengolahan kakao lebih “percaya” pada pasokan impor yang dianggap lebih konsisten dari sisi kualitas dan volume. Ironisnya, harga biji kakao impor justru jauh lebih mahal, bahkan sempat hampir dua kali lipat harga biji lokal. Meski demikian, industri tetap memilih impor karena pasokan domestik dinilai tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
Faktor kebijakan turut memperkuat kecenderungan ini, seperti pelonggaran pajak impor bahan baku yang membuat biji kakao impor relatif lebih mudah dan menarik bagi industri. Akibatnya, rantai nilai kakao domestik terputus. Biji kakao lokal yang sebenarnya berpotensi besar gagal terserap oleh industri pengolahan dalam negeri.
Dampak terberat dari situasi ini dirasakan langsung oleh petani kakao rakyat, yang selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Menurunnya serapan industri terhadap kakao lokal membuat harga di tingkat petani stagnan dan pendapatan sulit meningkat.
Banyak petani kehilangan minat dan beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit atau karet. Peralihan ini mempercepat penyusutan kebun kakao produktif. Dari sekitar 1,3 juta hektare lahan kakao, hanya sebagian yang masih produktif, sementara sisanya rusak atau belum menghasilkan.
Kondisi ini diperparah oleh tanaman yang menua, serangan hama dan penyakit, serta tekanan perubahan iklim. Jika dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan salah satu komoditas strategis yang pernah mengangkatnya ke jajaran produsen kakao terbesar dunia.
Di sisi lain, industri hilir kakao justru tumbuh pesat dan mencatatkan prestasi global. Belasan pabrik besar beroperasi dengan kapasitas ratusan ribu ton per tahun, dan produk olahan kakao Indonesia, seperti cocoa butter, pasta, dan bubuk, menguasai berbagai pasar ekspor utama.
Namun di balik gemilangnya hilirisasi, tersimpan anomali mendasar, kebergantungan tinggi pada biji kakao impor. Nilai tambah besar justru mengalir ke luar negeri, sementara petani lokal belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Mengingat hampir seluruh kebun kakao dikelola oleh petani rakyat, kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa strategi kakao nasional perlu dibenahi agar rantai nilai dari kebun hingga pasar global benar-benar tersambung secara adil dan berkelanjutan.
Baca juga: Studi: Kakao dapat lindungi jantung dari dampak duduk terlalu lama
Revitalisasi hulu hingga hilir
Untuk mengurai dilema “ekspor tinggi tetapi impor bahan baku”, langkah pertama yang mendesak adalah memperkuat sektor hulu tanpa mengendurkan laju hilirisasi.
Revitalisasi kebun kakao harus dipercepat melalui peremajaan tanaman tua dan rusak dengan varietas unggul yang lebih produktif dan tahan hama. Ratusan ribu hektare kebun kakao saat ini membutuhkan replanting, dan meskipun anggaran sudah tersedia, skalanya masih belum sebanding dengan kebutuhan nasional.
Program ini perlu diperluas dan dipercepat, disertai distribusi bibit unggul serta penerapan teknik budidaya modern yang benar-benar menjangkau petani di sentra-sentra produksi kakao.
Langkah kedua adalah pembenahan pascapanen di tingkat petani, terutama praktik fermentasi dan pengeringan. Tanpa perbaikan mutu biji, kakao lokal akan terus kalah bersaing dengan impor.
Pelatihan dan pendampingan teknis harus digencarkan hingga ke desa disertai dukungan nyata seperti fasilitas fermentasi komunal dan insentif harga yang lebih menarik bagi biji fermentasi berkualitas. Selisih harga yang tipis saat ini belum cukup mendorong petani berinvestasi waktu dan tenaga untuk fermentasi yang benar.
Jika kualitas biji lokal meningkat dan konsisten, kepercayaan industri terhadap pasokan domestik akan tumbuh dengan sendirinya.
Langkah ketiga adalah memperkuat kemitraan rantai pasok antara petani dan industri, sekaligus menyelaraskan kebijakan fiskal agar berpihak pada bahan baku lokal.
Pola kemitraan offtaker, koperasi petani, atau korporasi petani perlu diperluas, dengan skema pembelian terjamin dan harga premium bagi kakao berkualitas. Di saat yang sama, insentif pajak sebaiknya diarahkan untuk mendorong industri menyerap biji kakao domestik, bukan mempermudah impor.
Baca juga: Kemendag: Suplai naik, harga biji kakao turun 14,5 persen
*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian
Kenaikan harga akibat anjloknya pasokan dari Afrika membuka peluang besar untuk mendongkrak pendapatan petani sekaligus memperkuat devisa ekspor. Namun realitas di lapangan justru berkebalikan.
Di tengah posisinya sebagai salah satu eksportir produk olahan kakao terbesar dunia, Indonesia malah bergantung pada impor biji kakao mentah untuk menggerakkan industrinya sendiri.
Paradoks pun mengemuka, pabrik pengolahan tumbuh pesat dan produknya laku keras di pasar global, sementara sektor hulu melemah dan semakin bergantung pada pasokan luar negeri.
Padahal, Indonesia pernah berjaya di panggung kakao dunia. Pada 2010, produksi nasional mencapai puncaknya sekitar 844 ribu ton dan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga produsen kakao global.
Namun sejak itu tren berbalik arah. Produksi kakao terus merosot hingga hanya sekitar 632 ribu ton pada 2023 seiring menyusutnya luas kebun dari 1,56 juta hektare menjadi 1,39 juta hektare dalam kurun empat tahun. Penurunan ini terjadi justru saat permintaan global cokelat terus meningkat.
Ironinya, di tengah produksi biji kakao yang stagnan, industri pengolahan dalam negeri justru melaju kencang. Ekspor produk olahan kakao Indonesia telah menembus ratusan ribu ton dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar AS (setara Rp16 triliun), menjadikan Indonesia eksportir cocoa butter terbesar kedua dunia.
Hilirisasi tampak sukses di atas kertas, tetapi fondasinya rapuh karena pasokan bahan baku lokal tak mencukupi.
Kesenjangan antara kapasitas industri dan produksi kebun menciptakan tekanan serius pada pasokan kakao nasional. Kebutuhan bahan baku industri domestik diperkirakan mendekati 400 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri tak mampu mengimbangi. Kekurangan ini ditutup dengan impor yang terus meningkat, bahkan mencapai ratusan ribu ton dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar berasal dari Ekuador.
Akibatnya, kapasitas terpasang pabrik yang mencapai sekitar 700 ribu ton per tahun baru dimanfaatkan sebagian. Indonesia menjadi eksportir besar kakao olahan, tetapi nilai tambah dari hilirisasi belum sepenuhnya dinikmati petani lokal.
Mutu biji lokal vs kebutuhan industri
Salah satu akar persoalan kakao nasional terletak pada mutu biji kakao lokal yang belum konsisten memenuhi standar industri. Dalam industri cokelat, fermentasi merupakan tahap krusial untuk membentuk cita rasa dan kualitas kimia biji kakao. Namun di tingkat petani, praktik fermentasi masih sangat terbatas.
Mayoritas petani menjual biji kakao kering tanpa fermentasi dengan harga lebih rendah, sementara biji kakao yang difermentasi dengan baik memiliki nilai jual lebih tinggi. Keterbatasan pengetahuan, sarana, dan pendampingan membuat proses fermentasi sering tidak optimal.
Industri pun kerap mengeluhkan kadar asam yang tinggi dan rasa yang tidak seragam meskipun standar nasional (SNI 2323:2008) telah mewajibkan fermentasi sebagai syarat mutu. Tanpa dukungan teknis yang memadai, standar tersebut sulit diterapkan secara luas di lapangan.
Kendala mutu ini membuat pabrik pengolahan kakao lebih “percaya” pada pasokan impor yang dianggap lebih konsisten dari sisi kualitas dan volume. Ironisnya, harga biji kakao impor justru jauh lebih mahal, bahkan sempat hampir dua kali lipat harga biji lokal. Meski demikian, industri tetap memilih impor karena pasokan domestik dinilai tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
Faktor kebijakan turut memperkuat kecenderungan ini, seperti pelonggaran pajak impor bahan baku yang membuat biji kakao impor relatif lebih mudah dan menarik bagi industri. Akibatnya, rantai nilai kakao domestik terputus. Biji kakao lokal yang sebenarnya berpotensi besar gagal terserap oleh industri pengolahan dalam negeri.
Dampak terberat dari situasi ini dirasakan langsung oleh petani kakao rakyat, yang selama ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Menurunnya serapan industri terhadap kakao lokal membuat harga di tingkat petani stagnan dan pendapatan sulit meningkat.
Banyak petani kehilangan minat dan beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit atau karet. Peralihan ini mempercepat penyusutan kebun kakao produktif. Dari sekitar 1,3 juta hektare lahan kakao, hanya sebagian yang masih produktif, sementara sisanya rusak atau belum menghasilkan.
Kondisi ini diperparah oleh tanaman yang menua, serangan hama dan penyakit, serta tekanan perubahan iklim. Jika dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan salah satu komoditas strategis yang pernah mengangkatnya ke jajaran produsen kakao terbesar dunia.
Di sisi lain, industri hilir kakao justru tumbuh pesat dan mencatatkan prestasi global. Belasan pabrik besar beroperasi dengan kapasitas ratusan ribu ton per tahun, dan produk olahan kakao Indonesia, seperti cocoa butter, pasta, dan bubuk, menguasai berbagai pasar ekspor utama.
Namun di balik gemilangnya hilirisasi, tersimpan anomali mendasar, kebergantungan tinggi pada biji kakao impor. Nilai tambah besar justru mengalir ke luar negeri, sementara petani lokal belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Mengingat hampir seluruh kebun kakao dikelola oleh petani rakyat, kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa strategi kakao nasional perlu dibenahi agar rantai nilai dari kebun hingga pasar global benar-benar tersambung secara adil dan berkelanjutan.
Baca juga: Studi: Kakao dapat lindungi jantung dari dampak duduk terlalu lama
Revitalisasi hulu hingga hilir
Untuk mengurai dilema “ekspor tinggi tetapi impor bahan baku”, langkah pertama yang mendesak adalah memperkuat sektor hulu tanpa mengendurkan laju hilirisasi.
Revitalisasi kebun kakao harus dipercepat melalui peremajaan tanaman tua dan rusak dengan varietas unggul yang lebih produktif dan tahan hama. Ratusan ribu hektare kebun kakao saat ini membutuhkan replanting, dan meskipun anggaran sudah tersedia, skalanya masih belum sebanding dengan kebutuhan nasional.
Program ini perlu diperluas dan dipercepat, disertai distribusi bibit unggul serta penerapan teknik budidaya modern yang benar-benar menjangkau petani di sentra-sentra produksi kakao.
Langkah kedua adalah pembenahan pascapanen di tingkat petani, terutama praktik fermentasi dan pengeringan. Tanpa perbaikan mutu biji, kakao lokal akan terus kalah bersaing dengan impor.
Pelatihan dan pendampingan teknis harus digencarkan hingga ke desa disertai dukungan nyata seperti fasilitas fermentasi komunal dan insentif harga yang lebih menarik bagi biji fermentasi berkualitas. Selisih harga yang tipis saat ini belum cukup mendorong petani berinvestasi waktu dan tenaga untuk fermentasi yang benar.
Jika kualitas biji lokal meningkat dan konsisten, kepercayaan industri terhadap pasokan domestik akan tumbuh dengan sendirinya.
Langkah ketiga adalah memperkuat kemitraan rantai pasok antara petani dan industri, sekaligus menyelaraskan kebijakan fiskal agar berpihak pada bahan baku lokal.
Pola kemitraan offtaker, koperasi petani, atau korporasi petani perlu diperluas, dengan skema pembelian terjamin dan harga premium bagi kakao berkualitas. Di saat yang sama, insentif pajak sebaiknya diarahkan untuk mendorong industri menyerap biji kakao domestik, bukan mempermudah impor.
Baca juga: Kemendag: Suplai naik, harga biji kakao turun 14,5 persen
*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian