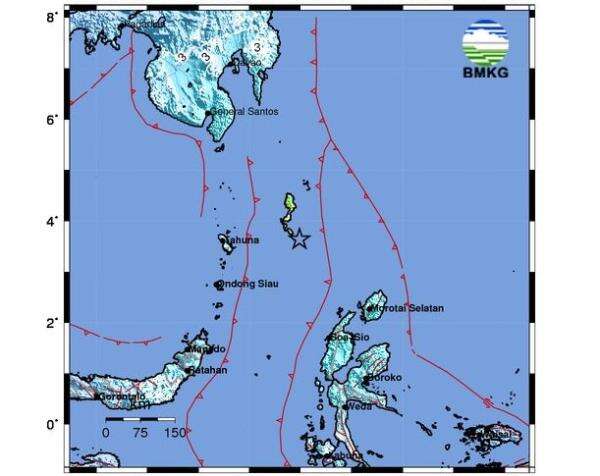JAKARTA, KOMPAS – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang serius. Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi merupakan manifestasi nyata kedaulatan rakyat.
Upaya memindahkan kembali hak memilih dari rakyat ke DPRD berarti mereduksi demokrasi menjadi urusan elite dan menghapus akuntabilitas kepala dearah kepada warga.
Peneliti Themis Indonesia, Fadli Ramadhanil, mengatakan, alasan ongkos politik tinggi apabila pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak terlalu relevan. Sebab, jika dicermati, ongkos politik yang dikeluarkan kandidat lebih banyak untuk membayar mahar politik ke partai politik dan politik uang. Kedua tindakan tersebut merupakan perilaku yang diharamkan dalam pilkada.
“Alasan memberangus pemilihan langsung kepala daerah dengan mengedepankan alasan pemborosan anggaran, biaya yang sangat besar, itu jelas satu alasan yang dicari-cari sebetulnya,” kata Fadli, dalam konferensi pers sekaligus peluncuran miniriset berjudul ”Tipu Daya Pilkada di DPRD” yang digelar secara luring dan daring, Minggu (11/1/2012).
Apabila ditelisik lebih detil, menurut Fadli, sebetulnya apa yang menyebabkan biaya penyelenggaraan pilkada itu besar. Salah satu yang membuat biaya pilkada itu besar justru adalah tindakan-tindakan dari peserta pilkada atau kemudian aktivitas-aktivitas yang sebetulnya sudah tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal itu di antaranya biaya pembayaran tiket pencalonan atau biaya membeli perahu.
“Jika dibandingkan dengan cost kampanye, jelas biaya untuk membeli tiket pencalonan pilkada itu akan jauh lebih besar,” kata Fadli yang juga menyebut politik uang dengan berbagai modus dan melanggar UU Pilkada, itu juga menyedot biaya pilkada.
Ada banyak dimensi yang mestinya dilakukan asesmen secara detail untuk kemudian menyimpulkan biaya penyelenggaraan pilkada itu besar.
Hal lain yang perlu ditelisik adalah penggunaan anggaran secara detail. Sebab, Fadhil mencurigai adanya pos-pos anggaran yang masuk ke dalam anggaran pilkada tetapi sebenarnya digunakan untuk hal yang tidak berkaitan atau mendukung penyelenggaraan pilkada. Misalnya, sewa mobil dinas berlebihan, perbaikan/renovasi kantor dan segala macam momentum pilkada.
“Jadi, ada banyak dimensi yang mestinya dilakukan asesmen secara detail untuk kemudian menyimpulkan biaya penyelenggaraan pilkada itu besar. Kalau kita bandingkan misalnya dengan biaya penyelenggaraan pemilu nasional, bagaimana besar biaya penyeleggaraan pemilu nasionalnya? KPU-nya malah melakukan penyewaan private jet, ya pasti besarlah biaya penyelenggaraannya,” sindir Fadli.
Oleh karena itu, menurutnya, publik perlu mewaspadai perilaku elite politik atau oknum penyelenggara yang membuat biaya pilkada membengkak. Jangan malah sebaliknya, yang diberangus adalah hak pemilih untuk menentukan kepala daerah.
Fadhil mengatakan, pilihan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD juga merupakan pilihan yang cacat dalam sistem presidensial. Sebab, tidak ada logikanya pemegang kekuasaan eksekutif dipilih oleh anggota DPR untuk menjalankan kekuasaannya. “Jadi, ini pilihan yang cacat secara konsep dan secara sistem,” ujarnya.
Berdasarkan miniriset yang dilakukan Themis, Peneliti Themis Indonesia, Kafin Muhammad, mengatakan, dalil mengenai anggaran negara minim atau anggaran terlalu besar untuk biaya pilkada tidak dapat dibenarkan. Sebab, Indonesia secara nyata masih memiliki anggaran yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang terus berjalan.
Misalnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada pembangunan tahap I (2022-2024) anggaran yang dialokasikan Rp 89 triliun, sementara pembangunan tahap II (2025-2029) dialokasikan Rp 48,8 triliun. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun sedangkan DIPA tahun ini Rp 6,26 triliun. Anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 meningkat menjadi RP 268.000 triliun dari sebelumnya Rp 116.649,7 triliun.
Menurut Kafin, dari data tersebut, anggaran penyelenggaraan pilkada seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Indonesia. Sebab, ada banyak anggaran digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan atau program lain yang pada pelaksanaannya jauh dari kata sempurna.
Mengacu pada dana penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wapres, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 71,3 trilun yang dilaksanakan dalam kurun tiga tahun. Rinciannya, Rp 3,1 triliun dikucurkan pada 2022, Rp 30 trilun pada tahun 2023, dan Rp 38 triliun dialokasikan pada 2024.
Wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD sebenarnya bukan isu yang baru pertama kali dilontarkan. Pada tahun 2014, wacana ini sempat bergulir tetapi kemudian tidak berhasil. Pada 2025, wacana ini kembali bergulir ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melontarkan isu ini dalam puncak perayaan HUT Partai Golkar.
Ibnu khawatir potensi gagasan ini lolos dalam revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada akan lolos.
Wacana ini kemudian disambut oleh partai-partai lain, khususnya partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Geridra, Partai Nasdem, dan partai Demokrat.
Peneliti Themis Indonesia lainnya, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan, koalisi partai pendukung pilkada melalui DPRD menguasai kursi yang besar di DPR. Tinggal beberapa partai, di antaranya PDI-P, yang belum menyatakan sikap. Namun, apabila dilihat perbandingan jumlah kursinya, Ibnu khawatir potensi gagasan ini lolos dalam revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada akan lolos.
“Ini menjadi salah satu tantangan kita. Makanya, kita perlu untuk membangun jaringan, bagaimana kekuatan masyarakat, kekuatan warga, kelompok masyarakat sipil untuk menolak wacana regresi demokrasi ini,” kata dia.

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2024%2F11%2F27%2F5c11c1d22b5f5d835b33e1f8508783b4-1000510094.jpg)