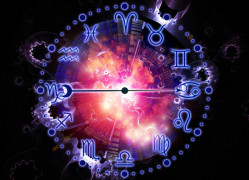Pertanyaan paling jarang diajukan dalam tragedi Palestina bukanlah soal moral, melainkan soal ekonomi: Bagaimana Israel membiayai penjajahan dan genosida yang telah berlangsung lebih dari 75 tahun?
Pertanyaan ini relevan ketika laporan Reuters mencatat Israel menghabiskan sekitar 31 miliar dolar AS hanya untuk dua tahun perang di Gaza dan Lebanon. Jika Palestina tidak kaya sumber daya alam, dari mana logika ekonomi penjajahan itu berasal?
Jawabannya sederhana sekaligus mengerikan: Palestina bukan sekadar wilayah jajahan, melainkan juga sebuah laboratorium.
Tidak ada yang menyangkal bahwa Zionisme dan gagasan mengenai tanah yang dijanjikan berperan dalam proyek kolonial Israel. Namun, sejarah kolonialisme selalu mengajarkan satu hal: ideologi tidak pernah bekerja sendirian. Kolonialisme bertahan karena ia menguntungkan. Dengan bahasa paling sederhana, biaya harus lebih kecil dari pendapatan.
Di sinilah buku Antony Loewenstein, Laboratorium Palestina, menjadi penting. Loewenstein menunjukkan bahwa kolonialisme Israel berbeda dari kolonialisme klasik. Palestina tidak dieksploitasi untuk rempah, mineral, atau perkebunan, tetapi untuk satu komoditas yang jauh lebih bernilai di era modern: teknologi militer dan keamanan.
Sejak Perang Enam Hari 1967, Israel secara sistematis membangun industri senjata dalam negeri. Alasannya pragmatis: Israel tidak bisa selamanya bergantung pada Amerika Serikat dan negara-negara Barat, sementara ia menganggap dirinya dikepung musuh regional (Loewenstein, 2025, hlm. 41–42). Dari sini, penjajahan Palestina berubah fungsi dari konflik teritorial menjadi arena uji coba.
Dalam bukunya, Loewenstein mendokumentasikan keterlibatan Israel dalam perdagangan senjata dengan rezim-rezim despotik di berbagai belahan dunia, mulai dari Chile hingga Myanmar. Israel—bersama Amerika Serikat—berperan dalam kejatuhan Presiden Chile Salvador Allende pada 1973.
Israel kemudian menyokong pemimpin kudeta, Augusto Pinochet—yang menjadi diktator Chile hingga 1990—melalui penjualan senjata. Pola serupa juga dilakukan Israel dengan mendukung junta militer Myanmar, rezim yang kita ketahui menindas kelompok pro-demokrasi dan bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya.
Dalam bisnis senjatanya, Israel tidak mengenal batas hak asasi manusia. Secara sadar, Israel memainkan peran sebagai perpanjangan tangan kotor Amerika Serikat, seperti terungkap dalam pernyataan politisi Likud, Yohanah Ramati.
Bisnis senjata ini dinilai amat krusial bagi Israel. Bahkan, “Israel mengabaikan produksi jeruk demi granat tangan.” (Zabner, dalam Loewenstein, 2025, hlm. 42)
Dampak dari kebijakan pasca-1967 ini sangat signifikan. Loewenstein mencatat bahwa Israel memiliki sekitar 6.000 perusahaan rintisan di bidang persenjataan, mulai dari rudal, roket, hingga senjata serbu. Tahun 2021 menjadi tahun terbaik bagi industri senjata Israel dengan omzet mencapai 11,3 miliar dolar AS, meningkat 55 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Israel tidak hanya menjual senjata konvensional. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam teknologi surveilans global. Produk paling terkenal adalah Pegasus, perangkat lunak mata-mata buatan NSO Group yang digunakan untuk meretas ponsel jurnalis, aktivis, dan oposisi politik di berbagai negara. Salah satu kasus paling brutal adalah pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi.
Pegasus bukan anomali, melainkan model bisnis. NSO mengeklaim memiliki klien di 40 negara. Mengacu pada laporan investigas Jaring, beberapa Lembaga di Indonesia—seperti Kepolisian, BNN, dan BIN—menjadi pelanggan Pegasus. Biaya sewa teknologi ini mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Bahkan, menurut Privacy International, Israel memiliki jumlah perusahaan surveilans per kapita tertinggi di dunia, melampaui Amerika Serikat dan Inggris. (Loewenstein, 2025, hlm. 248)
Aspek lain yang menjadi nilai jual perusahaan-perusahaan Israel di tingkat global adalah bisnis keamanan perbatasan. Perusahaan Israel seperti Elbit dan Israel Aerospace Industries bekerja sama dengan Frontex—lembaga penjaga perbatasan Uni Eropa—untuk memasok drone dan teknologi surveilans guna menghadang pengungsi dari Afrika dan Timur Tengah agar tidak memasuki Eropa. Operasi Frontex kerap berujung pada hilangnya nyawa pengungsi dan telah lama menjadi sorotan organisasi hak asasi manusia di Eropa.
Di Amerika Serikat, Elbit juga menggarap proyek perbatasan AS–Meksiko melalui kontrak 500–700 juta dolar AS untuk pagar virtual, yang menurut studi Eraham College (2022) berkontribusi pada lonjakan kematian imigran hingga 643 persen akibat militerisasi perbatasan. (Loewenstein, 2025, hlm. 204)
Mengapa teknologi Israel begitu diminati? Karena semuanya berlabel battle-tested. Dan medan ujinya bernama Palestina.
Seluruh teknologi yang mereka jual disempurnakan melalui uji coba langsung di Palestina. Dalam setiap serangan ke Gaza, Israel tidak hanya menjalankan genosida, tetapi juga menguji akurasi senjatanya. Teknologi surveilans seperti Pegasus pertama kali diterapkan pada penduduk Tepi Barat, khususnya di Hebron.
Di kota ini, Israel menjalankan surveilans massal: ponsel warga diretas, puluhan ribu kamera CCTV dipasang untuk memantau jalan bahkan rumah, dan pos militer memindai wajah setiap warga Palestina yang melintas menggunakan teknologi Blue Wolf. (Loewenstein, 2025, hlm. 95)
Israel juga membangun tembok setinggi sembilan meter sepanjang 708 kilometer untuk memisahkan Gaza dari wilayah utama Israel. Tembok yang mengurung gaza dan menjadikannya penjara luar ruang terbesar di dunia.
Israel tidak hanya menjual senjata, tetapi juga menjual model dunia: dunia yang menganggap diskriminasi, segregasi, dan dominasi etnis sebagai kebijakan keamanan yang sah. Model inilah yang menginspirasi banyak pemimpin dunia, diantaranya Donald Trump. Saat membela kebijakan membangun tembok perbatasan AS–Meksiko dari kritik, Presiden Amerika Serikat tersebut menyampaikan, “Jika ingin tahu tembok efektif atau tidak, lihat Israel.”
Inilah inti ekonomi politik kolonialisme Israel. Palestina menjadi alat untuk membangun reputasi global, membuka pasar senjata, dan menciptakan ketergantungan politik. Semakin banyak negara bergantung pada teknologi Israel, semakin kecil kemungkinan mereka mengutuk kekejian Israel di Palestina.
Di titik ini, perjuangan Palestina bukan lagi isu lokal atau regional. Ia adalah perlawanan global terhadap normalisasi kolonialisme modern. Seusai membaca buku ini, saya teringat lagu lama dari Italia berjudul Rossa Palestina, penggalan liriknya berbunyi “Every shot fired at the Zionist enemy, hits those who rule in Italy.” Sebaliknya, setiap peluru yang diuji di Gaza, pada akhirnya, menopang sistem penindasan di tempat lain.