Jakarta (ANTARA) - Sepanjang 2025, ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut sejalan dengan proyeksi banyak ekonom.
Dalam kurun 12 bulan terakhir saja, dinamika geopolitik bergerak cepat. Mulai dari konflik regional yang tidak mereda, hingga kebijakan agresif negara adidaya turut mengubah lanskap perdagangan dunia.
Salah satu yang disorot tahun ini adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), atau yang populer disebut tarif Trump.
Kebijakan itu menuai kontroversi. Bagaimana tidak, tatkala Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden, pada 2 April 2025 ia mengumumkan kebijakan tarif resiprokal universal yang ia sebut sebagai America’s Liberation Day.
Bagi eksportir Indonesia, keputusan itu menjadi alarm dini.
Kala itu, AS menetapkan tarif dasar 10 persen bagi hampir seluruh barang impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari perhitungan tersebut, tarif untuk produk asal Indonesia melonjak hingga 32 persen.
Pada titik ini, kalkulasi perdagangan berubah drastis. Surplus dagang yang selama ini dibanggakan Indonesia mulai menghadapi tekanan seiring meningkatnya risiko penurunan daya saing produk nasional di pasar AS.
Sebenarnya, pasar AS memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Perlu diketahui bahwa AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China, dengan porsi pasar yang signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi ekspor Indonesia ke AS konsisten berada di kisaran 9 hingga 11 persen dalam lima tahun terakhir. Hubungan dagang ini juga ditopang oleh surplus perdagangan Indonesia yang relatif besar.
Hingga 2024, surplus Indonesia terhadap AS berada di rentang 14,4 miliar dolar AS hingga 19,3 miliar dolar AS, terutama ditopang ekspor tekstil, alas kaki, dan furnitur. Namun, dalam logika pemerintahan Trump, defisit perdagangan dipandang sebagai kerugian yang harus “dikoreksi”.
Pemerintah AS menilai Indonesia menerapkan sejumlah hambatan masuk (barrier), baik tarif maupun non-tarif, hingga 64 persen terhadap produk asal Amerika. Logika perhitungan inilah yang jadi dasar Trump menetapkan tarif balasan setengahnya, yakni 32 persen, pada awal April 2025.
Meski tarif kemudian diturunkan menjadi 19 persen, risikonya tetap membayangi dunia usaha nasional. Dari titik inilah proses perundingan panjang dan penuh aral dimulai.
Kabut proteksionisme AS
Kebijakan tarif resiprokal AS menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak nyaman. Di tengah retorika America First khas Partai Republik yang kembali dihidupkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak langsung.
Dampak paling nyata adalah kenaikan harga produk buatan Indonesia di rak-rak toko AS. Dalam teori permintaan, kenaikan harga hampir selalu berujung pada pergeseran konsumsi.
Konsumen AS berpotensi beralih ke produk dari negara dengan tarif lebih rendah atau ke produk domestik. Bagi eksportir Indonesia, implikasinya jelas yakni penyusutan pesanan dan penurunan pangsa pasar.
Tekanan ini terasa paling berat di sektor padat karya. Industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, serta furnitur dan produk kayu menjadi kelompok paling rentan. Ketika ekspor melambat, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.
Efek lanjutan dari melemahnya ekspor adalah tekanan pada nilai tukar rupiah.
Penurunan ekspor ke AS berpotensi mengurangi aliran devisa, sementara kebijakan proteksionisme Trump kerap disertai penguatan dolar AS. Kombinasi ini memperbesar tekanan depresiasi rupiah.
Nilai tukar yang melemah pada gilirannya meningkatkan biaya impor bahan baku bagi industri dalam negeri. Tekanan biaya produksi berpotensi diteruskan ke harga barang, memicu inflasi domestik.
Dalam skenario ini, dampak tarif tidak lagi bersifat sektoral, melainkan merambat ke stabilitas makro secara keseluruhan.
Kompromi kesepakatan dagang
Pada 15 Juli, Trump mengumumkan hanya akan menerapkan tarif 19 persen terhadap produk asal Indonesia. Keputusan ini menjadi hasil diplomasi tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebagai imbalan, Indonesia membuat komitmen kerja sama dagang baru dengan AS. Pemerintah memilih jalur negosiasi dengan melakukan “barter” kebijakan, sebuah langkah kompromi yang kerap dianggap sebagai pilihan paling realistis.
Salah satu kesepakatan utamanya adalah komitmen Indonesia meningkatkan impor produk AS senilai 19 miliar dolar AS. Kesepakatan ini mencakup pembelian energi seperti gas alam cair (LNG) hingga bahan bakar minyak (BBM) senilai 15 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian AS seperti gandum, kedelai, dan jagung senilai 4,5 miliar dolar AS, serta kelanjutan pembelian pesawat Boeing.
Pemerintah juga menjanjikan penghapusan sejumlah hambatan non-tarif melalui deregulasi, termasuk peninjauan aturan konten lokal (TKDN) dan penyelesaian isu aliran data lintas batas.
Bahkan, Indonesia menawarkan investasi langsung di AS untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga Amerika, sejalan dengan agenda politik Trump. Namun, kompromi ini menyimpan konsekuensi jangka panjang.
Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman meminta pemerintah mewaspadai risiko makroekonomi nasional akibat kesepakatan tarif tersebut.
Menurut dia, komitmen pembelian besar-besaran itu berpotensi menekan neraca transaksi berjalan.
“Secara prinsip ekonomi, ini mencerminkan pola perdagangan yang tidak setara, atau asymmetric trade, dengan akses ekspor diberikan yang berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang dan jasa dari AS,” katanya.
Tanpa kenaikan ekspor komoditas lain, risiko balance of payment shock bisa muncul, terutama jika harga energi global berfluktuasi tajam. Akses pasar produk AS yang makin terbuka juga berpotensi menekan produsen lokal di sektor aviasi, energi, dan pertambangan.
Sebagai antisipasi, Rizal menyarankan pemerintah mengintensifkan kerja sama dagang dengan pasar ekspor alternatif guna menjaga keseimbangan struktur perdagangan.
Kendati demikian, jalur negosiasi tetap mendapat apresiasi.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai langkah ini lebih rasional ketimbang membalas dengan tarif yang lebih tinggi. Sebab, pemerintah juga perlu memahami posisi daya tawar Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Jalan penuh aral
Tak cukup dengan tarif 19 persen, Tim Negosiasi RI terus melobi pemerintahan Trump agar memberikan tarif nol persen untuk produk sumber daya alam (SDA) unggulan Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit (CPO).
Sebelumnya AS telah mengecualikan sejumlah produk pertanian, termasuk kakao, dari tarif 19 persen melalui Executive Orders pada 14 November.
Teranyar, Airlangga menyampaikan pihaknya telah bertemu Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer. Meski belum jelas hasil akhirnya, pemerintah mengklaim substansi perjanjian telah disepakati.
Pemerintah menargetkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Saat ini, dokumen perjanjian disebut memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa. Tim teknis kedua negara dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada pekan kedua Januari 2026.
Syahdan, bagi Indonesia, negosiasi ini menjadi ujian sejauh mana kepentingan nasional dapat dijaga di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik yang mengeras.
Langkah negosiasi bisa dinilai sebagai pilihan paling rasional bagi negara berkembang. Sebaliknya, saling berbalas tarif justru berisiko menjadi langkah yang gegabah.
Berkaca pada India dan Brasil yang dikenakan tarif 50 persen, China 34 persen, serta Myanmar dan Laos 40 persen, posisi Indonesia relatif masih terkendali.
Meski pasar AS tetap penting, ketergantungan tunggal jelas bukan strategi jangka panjang. Sebab, dunia kini bergerak menuju poros-poros ekonomi baru.
Indonesia perlu aktif berdiplomasi menjemput peluang, agar tak sekadar menjadi objek tarik-menarik kepentingan negara adidaya.
Sementara hegemoni AS saat ini kian terkikis, tercermin dari aksi saling balas tarif dan boikot antara AS, Rusia, dan China.
Dalam lanskap ini, Indonesia dituntut bersikap kalkulatif menghitung risiko ekonomi sembari menjaga hubungan bilateral sebagaimana pepatah Tiongkok kuno yang dikutip Prabowo: "Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak."
Dalam kurun 12 bulan terakhir saja, dinamika geopolitik bergerak cepat. Mulai dari konflik regional yang tidak mereda, hingga kebijakan agresif negara adidaya turut mengubah lanskap perdagangan dunia.
Salah satu yang disorot tahun ini adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), atau yang populer disebut tarif Trump.
Kebijakan itu menuai kontroversi. Bagaimana tidak, tatkala Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden, pada 2 April 2025 ia mengumumkan kebijakan tarif resiprokal universal yang ia sebut sebagai America’s Liberation Day.
Bagi eksportir Indonesia, keputusan itu menjadi alarm dini.
Kala itu, AS menetapkan tarif dasar 10 persen bagi hampir seluruh barang impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari perhitungan tersebut, tarif untuk produk asal Indonesia melonjak hingga 32 persen.
Pada titik ini, kalkulasi perdagangan berubah drastis. Surplus dagang yang selama ini dibanggakan Indonesia mulai menghadapi tekanan seiring meningkatnya risiko penurunan daya saing produk nasional di pasar AS.
Sebenarnya, pasar AS memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Perlu diketahui bahwa AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China, dengan porsi pasar yang signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi ekspor Indonesia ke AS konsisten berada di kisaran 9 hingga 11 persen dalam lima tahun terakhir. Hubungan dagang ini juga ditopang oleh surplus perdagangan Indonesia yang relatif besar.
Hingga 2024, surplus Indonesia terhadap AS berada di rentang 14,4 miliar dolar AS hingga 19,3 miliar dolar AS, terutama ditopang ekspor tekstil, alas kaki, dan furnitur. Namun, dalam logika pemerintahan Trump, defisit perdagangan dipandang sebagai kerugian yang harus “dikoreksi”.
Pemerintah AS menilai Indonesia menerapkan sejumlah hambatan masuk (barrier), baik tarif maupun non-tarif, hingga 64 persen terhadap produk asal Amerika. Logika perhitungan inilah yang jadi dasar Trump menetapkan tarif balasan setengahnya, yakni 32 persen, pada awal April 2025.
Meski tarif kemudian diturunkan menjadi 19 persen, risikonya tetap membayangi dunia usaha nasional. Dari titik inilah proses perundingan panjang dan penuh aral dimulai.
Kabut proteksionisme AS
Kebijakan tarif resiprokal AS menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak nyaman. Di tengah retorika America First khas Partai Republik yang kembali dihidupkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak langsung.
Dampak paling nyata adalah kenaikan harga produk buatan Indonesia di rak-rak toko AS. Dalam teori permintaan, kenaikan harga hampir selalu berujung pada pergeseran konsumsi.
Konsumen AS berpotensi beralih ke produk dari negara dengan tarif lebih rendah atau ke produk domestik. Bagi eksportir Indonesia, implikasinya jelas yakni penyusutan pesanan dan penurunan pangsa pasar.
Tekanan ini terasa paling berat di sektor padat karya. Industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, serta furnitur dan produk kayu menjadi kelompok paling rentan. Ketika ekspor melambat, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.
Efek lanjutan dari melemahnya ekspor adalah tekanan pada nilai tukar rupiah.
Penurunan ekspor ke AS berpotensi mengurangi aliran devisa, sementara kebijakan proteksionisme Trump kerap disertai penguatan dolar AS. Kombinasi ini memperbesar tekanan depresiasi rupiah.
Nilai tukar yang melemah pada gilirannya meningkatkan biaya impor bahan baku bagi industri dalam negeri. Tekanan biaya produksi berpotensi diteruskan ke harga barang, memicu inflasi domestik.
Dalam skenario ini, dampak tarif tidak lagi bersifat sektoral, melainkan merambat ke stabilitas makro secara keseluruhan.
Kompromi kesepakatan dagang
Pada 15 Juli, Trump mengumumkan hanya akan menerapkan tarif 19 persen terhadap produk asal Indonesia. Keputusan ini menjadi hasil diplomasi tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebagai imbalan, Indonesia membuat komitmen kerja sama dagang baru dengan AS. Pemerintah memilih jalur negosiasi dengan melakukan “barter” kebijakan, sebuah langkah kompromi yang kerap dianggap sebagai pilihan paling realistis.
Salah satu kesepakatan utamanya adalah komitmen Indonesia meningkatkan impor produk AS senilai 19 miliar dolar AS. Kesepakatan ini mencakup pembelian energi seperti gas alam cair (LNG) hingga bahan bakar minyak (BBM) senilai 15 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian AS seperti gandum, kedelai, dan jagung senilai 4,5 miliar dolar AS, serta kelanjutan pembelian pesawat Boeing.
Pemerintah juga menjanjikan penghapusan sejumlah hambatan non-tarif melalui deregulasi, termasuk peninjauan aturan konten lokal (TKDN) dan penyelesaian isu aliran data lintas batas.
Bahkan, Indonesia menawarkan investasi langsung di AS untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga Amerika, sejalan dengan agenda politik Trump. Namun, kompromi ini menyimpan konsekuensi jangka panjang.
Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman meminta pemerintah mewaspadai risiko makroekonomi nasional akibat kesepakatan tarif tersebut.
Menurut dia, komitmen pembelian besar-besaran itu berpotensi menekan neraca transaksi berjalan.
“Secara prinsip ekonomi, ini mencerminkan pola perdagangan yang tidak setara, atau asymmetric trade, dengan akses ekspor diberikan yang berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang dan jasa dari AS,” katanya.
Tanpa kenaikan ekspor komoditas lain, risiko balance of payment shock bisa muncul, terutama jika harga energi global berfluktuasi tajam. Akses pasar produk AS yang makin terbuka juga berpotensi menekan produsen lokal di sektor aviasi, energi, dan pertambangan.
Sebagai antisipasi, Rizal menyarankan pemerintah mengintensifkan kerja sama dagang dengan pasar ekspor alternatif guna menjaga keseimbangan struktur perdagangan.
Kendati demikian, jalur negosiasi tetap mendapat apresiasi.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai langkah ini lebih rasional ketimbang membalas dengan tarif yang lebih tinggi. Sebab, pemerintah juga perlu memahami posisi daya tawar Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Jalan penuh aral
Tak cukup dengan tarif 19 persen, Tim Negosiasi RI terus melobi pemerintahan Trump agar memberikan tarif nol persen untuk produk sumber daya alam (SDA) unggulan Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit (CPO).
Sebelumnya AS telah mengecualikan sejumlah produk pertanian, termasuk kakao, dari tarif 19 persen melalui Executive Orders pada 14 November.
Teranyar, Airlangga menyampaikan pihaknya telah bertemu Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer. Meski belum jelas hasil akhirnya, pemerintah mengklaim substansi perjanjian telah disepakati.
Pemerintah menargetkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Saat ini, dokumen perjanjian disebut memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa. Tim teknis kedua negara dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada pekan kedua Januari 2026.
Syahdan, bagi Indonesia, negosiasi ini menjadi ujian sejauh mana kepentingan nasional dapat dijaga di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik yang mengeras.
Langkah negosiasi bisa dinilai sebagai pilihan paling rasional bagi negara berkembang. Sebaliknya, saling berbalas tarif justru berisiko menjadi langkah yang gegabah.
Berkaca pada India dan Brasil yang dikenakan tarif 50 persen, China 34 persen, serta Myanmar dan Laos 40 persen, posisi Indonesia relatif masih terkendali.
Meski pasar AS tetap penting, ketergantungan tunggal jelas bukan strategi jangka panjang. Sebab, dunia kini bergerak menuju poros-poros ekonomi baru.
Indonesia perlu aktif berdiplomasi menjemput peluang, agar tak sekadar menjadi objek tarik-menarik kepentingan negara adidaya.
Sementara hegemoni AS saat ini kian terkikis, tercermin dari aksi saling balas tarif dan boikot antara AS, Rusia, dan China.
Dalam lanskap ini, Indonesia dituntut bersikap kalkulatif menghitung risiko ekonomi sembari menjaga hubungan bilateral sebagaimana pepatah Tiongkok kuno yang dikutip Prabowo: "Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak."
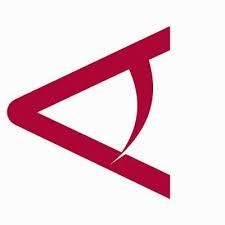


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5426825/original/087789000_1764318243-173103.jpg)



