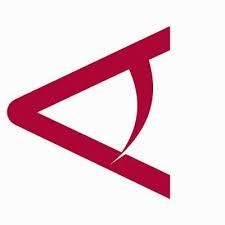Jakarta (ANTARA) - Ketika Presiden Venezuela Nicolás Maduro digiring ke pengadilan federal di New York pada awal Januari 2026 digambarkan oleh sejumlah media sebagai operasi internasional paling dramatis.
Banyak yang terpukau oleh kecepatan dan ketepatan taktis operasi Amerika Serikat di Venezuela. Tidak lebih, hanya 5 jam saja. Kejutan teknis dan kekuatan logistik serangan dengan kombinasi teknologi militer tanpa tembakan, sistem informasi, dan algoritma ekonomi yang mematikan telah meruntuhkan kedaulatan Venezuela dalam sekejap.
Operasi itu bukan sekadar “militer” atau “penegakan hukum” biasa, tetapi perwujudan lawfare yang dimotori oleh kursi kekuatan blok politik global AS.
Ini adalah bentuk operasi perang terbaru. Lawfare, menggunakan alasan moral dan instrumen hukum ekstrateritorial sebagai legitimasi serangan terhadap negara lain.
Dalam konteks Venezuela, negara maju mengklaim hak untuk mengeksekusi hukum domestiknya terhadap kepala negara di luar AS atas dugaan kejahatan yang dikaitkan dengan wilayah yuridiksinya, lalu membingkainya sebagai “penegakan hukum internasional.”
Tentu, ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, dan supremasi hukum internasional masih relevan jika hukum nasional dapat menembus batas geografis secara sepihak?
Lihatlah fakta sejarah penggulingan dan penangkapan Saddam Hussein di Irak oleh AS dan sekutunya, dengan alasan hukum berupa dakwaan kepemilikan senjata pemusnah massal pada 2003. Saddam dihukum mati, meskipun tidak pernah terbukti menyimpan senjata pemusnah massal oleh pengadilan manapun.
Gaddafi di Libya menghadapi intervensi NATO atas nama doktrin hukum Responsibility to Protect (R2P), lalu rezimnya jatuh, setelah konflik berkepanjangan pada pada 2011. Hal yang sama diterapkan kepada Assad di Suriah, dengan cara kriminalisasi sejak 2023 hingga 2025, secara moral dan hukum, meskipun tidak pernah ditangkap secara paksa.
Sementara itu, Maduro ditetapkan berdasarkan indictment (dakwaan) federal oleh Juri Agung federal AS di Southern District of New York (SDNY) . Maduro dan keluarganya didakwa atas kejahatan narkoterorisme, yaitu penggunaan perdagangan narkotika untuk mendukung, membiayai, atau menjalankan tindakan terorisme, atau sebaliknya, penggunaan teror dan kekerasan untuk melindungi bisnis narkotika.
Berdasarkan dokumen hukum itu, AS menggerakkan intelijen dan militernya untuk mematikan aliran logistik Venezuela, sebelum akhirnya operasi militer dilaksanakan.
Dari fakta-fakta di atas, terlihat jelas bahwa hukum domestik dan opini moral dibentuk untuk melegitimasi sebuah invasi dan intervensi kedaulatan. Bagaimana mungkin instrumen hukum nasional sebuah negara dapat diberlakukan secara ekstrateritorial terhadap warga negara lain. Prinsip Westphalian tentang kedaulatan negara sebagai ruang kehidupan hukum yang independen secara nyata telah dilanggar.
Ini adalah pergeseran paradigma yang berbahaya. Bukan hanya hukum internasional diperlemah, tetapi batas wilayah sebagai ruang hukum nasional terdekontruksi oleh narasi normatif blok kekuatan politik global yang lebih kuat.
Dalam hukum internasional, imunitas kepala negara aktif diakui secara luas. Hanya setelah masa jabatan atau melalui mekanisme internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional tuduhan terhadap kepala negara dapat ditindaklanjuti, tanpa merusak norma kedaulatan.
Strategi lawfare mencoba untuk circumvent (menghindari) imunitas itu dengan membingkai tindakan sebagai penegakan hukum domestik terhadap “buronan kriminal”. Hal ini membuka celah bagi penggunaan hukum sebagai alat dominasi.
Diplomasi damai
Ada implikasi strategis yang lebih luas dari pendekatan lawfare ini, yaitu terancamnya kedaulatan nasional, baik dari sisi hukum, politik dan teknologi. Kekuatan politik negara-negara blok tertentu tidak hanya berusaha untuk terus mendikte perilaku politik dan ekonomi negara-negara lain, tetapi juga mengancam dengan dalih penegakan hukum.
Sementara pada aspek teknologi, kesenjangan digital adalah makanan empuk untuk dimainkan. Dari kasus Venezuela kita dapat mengambil pelajaran jika sebuah negara kuat menekan entitas finansial, sistem bank, dan logistik negara lain dari jarak ribuan kilometer melalui algoritma dan artificial intelligence, maka kedaulatan sebuah negara dalam ancaman serius.
Ini menjadi alarm bagi Indonesia. Republik ini sedang berada di fase penting sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis di Asia Tenggara, dan populasi besar menjadikan Indonesia sebagai aktor signifikan di kancah global.
Hanya saja, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, sistem keuangan global yang dikontrol oleh kekuatan besar, dan kekurangan kapasitas daya saing digital menempatkan Indonesia pada posisi rentan jika terjebak dalam jaring lawfare.
Dalam menghadapi dinamika geopolitik semacam itu, Indonesia tidak bisa berdiam diri dengan doktrin politik luar negeri “bebas aktif.” Indonesia harus berani menyuarakan perdamaian dunia dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara.
Penerapan pendekatan strategis yang menggabungkan diplomasi hukum internasional, pembangunan kapasitas digital dan finansial nasional, serta pembentukan koalisi Global South untuk menegakkan prinsip-prinsip mendasar hukum internasional demi tercapainya perdamaian dunia layak ditempuh oleh Indonesia.
Indonesia harus berada di garis depan dalam memperjuangkan supremasi hukum internasional melalui mekanisme multilateral, seperti PBB, G20, dan pengadilan internasional yang diakui secara universal.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, kejahatan perang, atau kekejaman struktural harus berjalan melalui proses internasional yang sah, bukan melalui hukum domestik satu negara yang memiliki kekuatan global.
Indonesia, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota aktif berbagai forum internasional, dapat memfasilitasi dialog dan reformasi struktural agar yurisdiksi ekstrateritorial tidak disalahgunakan.
Indonesia juga harus memperkuat koordinasi dengan negara-negara Global South lain yang memiliki pengalaman serupa untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
Melalui organisasi, seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN Regional Forum, dan kerja sama Asia-Afrika, Indonesia dapat membantu merumuskan charter atau deklarasi yang menegaskan kembali imunitas kepala negara yang masih menjabat, batasan yurisdiksi ekstrateritorial, dan prosedur multilateral untuk penanganan kejahatan lintas negara.
Dengan membangun konsensus di antara negara berkembang, Indonesia tidak hanya melindungi diri dari potensi lawfare, tetapi juga memperkuat tatanan hukum internasional yang lebih seimbang.
Karena jika hukum dapat menjadi senjata, maka diplomasi harus menjadi tameng, menjadi pedang yang melindungi setiap bangsa dari dominasi yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip keadilan universal. Indonesia harus siap, bukan hanya duduk di meja makan dunia, tetapi menentukan aturan mainnya. Ini adalah modal diplomasi untuk memperkuat visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
*) Ngasiman Djoyonegoro adalah analis intelijen, pertahanan dan keamanan, penulis buku Sketsa Diplomasi dan Pertahanan Nasional dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru
Banyak yang terpukau oleh kecepatan dan ketepatan taktis operasi Amerika Serikat di Venezuela. Tidak lebih, hanya 5 jam saja. Kejutan teknis dan kekuatan logistik serangan dengan kombinasi teknologi militer tanpa tembakan, sistem informasi, dan algoritma ekonomi yang mematikan telah meruntuhkan kedaulatan Venezuela dalam sekejap.
Operasi itu bukan sekadar “militer” atau “penegakan hukum” biasa, tetapi perwujudan lawfare yang dimotori oleh kursi kekuatan blok politik global AS.
Ini adalah bentuk operasi perang terbaru. Lawfare, menggunakan alasan moral dan instrumen hukum ekstrateritorial sebagai legitimasi serangan terhadap negara lain.
Dalam konteks Venezuela, negara maju mengklaim hak untuk mengeksekusi hukum domestiknya terhadap kepala negara di luar AS atas dugaan kejahatan yang dikaitkan dengan wilayah yuridiksinya, lalu membingkainya sebagai “penegakan hukum internasional.”
Tentu, ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, dan supremasi hukum internasional masih relevan jika hukum nasional dapat menembus batas geografis secara sepihak?
Lihatlah fakta sejarah penggulingan dan penangkapan Saddam Hussein di Irak oleh AS dan sekutunya, dengan alasan hukum berupa dakwaan kepemilikan senjata pemusnah massal pada 2003. Saddam dihukum mati, meskipun tidak pernah terbukti menyimpan senjata pemusnah massal oleh pengadilan manapun.
Gaddafi di Libya menghadapi intervensi NATO atas nama doktrin hukum Responsibility to Protect (R2P), lalu rezimnya jatuh, setelah konflik berkepanjangan pada pada 2011. Hal yang sama diterapkan kepada Assad di Suriah, dengan cara kriminalisasi sejak 2023 hingga 2025, secara moral dan hukum, meskipun tidak pernah ditangkap secara paksa.
Sementara itu, Maduro ditetapkan berdasarkan indictment (dakwaan) federal oleh Juri Agung federal AS di Southern District of New York (SDNY) . Maduro dan keluarganya didakwa atas kejahatan narkoterorisme, yaitu penggunaan perdagangan narkotika untuk mendukung, membiayai, atau menjalankan tindakan terorisme, atau sebaliknya, penggunaan teror dan kekerasan untuk melindungi bisnis narkotika.
Berdasarkan dokumen hukum itu, AS menggerakkan intelijen dan militernya untuk mematikan aliran logistik Venezuela, sebelum akhirnya operasi militer dilaksanakan.
Dari fakta-fakta di atas, terlihat jelas bahwa hukum domestik dan opini moral dibentuk untuk melegitimasi sebuah invasi dan intervensi kedaulatan. Bagaimana mungkin instrumen hukum nasional sebuah negara dapat diberlakukan secara ekstrateritorial terhadap warga negara lain. Prinsip Westphalian tentang kedaulatan negara sebagai ruang kehidupan hukum yang independen secara nyata telah dilanggar.
Ini adalah pergeseran paradigma yang berbahaya. Bukan hanya hukum internasional diperlemah, tetapi batas wilayah sebagai ruang hukum nasional terdekontruksi oleh narasi normatif blok kekuatan politik global yang lebih kuat.
Dalam hukum internasional, imunitas kepala negara aktif diakui secara luas. Hanya setelah masa jabatan atau melalui mekanisme internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional tuduhan terhadap kepala negara dapat ditindaklanjuti, tanpa merusak norma kedaulatan.
Strategi lawfare mencoba untuk circumvent (menghindari) imunitas itu dengan membingkai tindakan sebagai penegakan hukum domestik terhadap “buronan kriminal”. Hal ini membuka celah bagi penggunaan hukum sebagai alat dominasi.
Diplomasi damai
Ada implikasi strategis yang lebih luas dari pendekatan lawfare ini, yaitu terancamnya kedaulatan nasional, baik dari sisi hukum, politik dan teknologi. Kekuatan politik negara-negara blok tertentu tidak hanya berusaha untuk terus mendikte perilaku politik dan ekonomi negara-negara lain, tetapi juga mengancam dengan dalih penegakan hukum.
Sementara pada aspek teknologi, kesenjangan digital adalah makanan empuk untuk dimainkan. Dari kasus Venezuela kita dapat mengambil pelajaran jika sebuah negara kuat menekan entitas finansial, sistem bank, dan logistik negara lain dari jarak ribuan kilometer melalui algoritma dan artificial intelligence, maka kedaulatan sebuah negara dalam ancaman serius.
Ini menjadi alarm bagi Indonesia. Republik ini sedang berada di fase penting sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis di Asia Tenggara, dan populasi besar menjadikan Indonesia sebagai aktor signifikan di kancah global.
Hanya saja, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, sistem keuangan global yang dikontrol oleh kekuatan besar, dan kekurangan kapasitas daya saing digital menempatkan Indonesia pada posisi rentan jika terjebak dalam jaring lawfare.
Dalam menghadapi dinamika geopolitik semacam itu, Indonesia tidak bisa berdiam diri dengan doktrin politik luar negeri “bebas aktif.” Indonesia harus berani menyuarakan perdamaian dunia dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara.
Penerapan pendekatan strategis yang menggabungkan diplomasi hukum internasional, pembangunan kapasitas digital dan finansial nasional, serta pembentukan koalisi Global South untuk menegakkan prinsip-prinsip mendasar hukum internasional demi tercapainya perdamaian dunia layak ditempuh oleh Indonesia.
Indonesia harus berada di garis depan dalam memperjuangkan supremasi hukum internasional melalui mekanisme multilateral, seperti PBB, G20, dan pengadilan internasional yang diakui secara universal.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, kejahatan perang, atau kekejaman struktural harus berjalan melalui proses internasional yang sah, bukan melalui hukum domestik satu negara yang memiliki kekuatan global.
Indonesia, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota aktif berbagai forum internasional, dapat memfasilitasi dialog dan reformasi struktural agar yurisdiksi ekstrateritorial tidak disalahgunakan.
Indonesia juga harus memperkuat koordinasi dengan negara-negara Global South lain yang memiliki pengalaman serupa untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
Melalui organisasi, seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN Regional Forum, dan kerja sama Asia-Afrika, Indonesia dapat membantu merumuskan charter atau deklarasi yang menegaskan kembali imunitas kepala negara yang masih menjabat, batasan yurisdiksi ekstrateritorial, dan prosedur multilateral untuk penanganan kejahatan lintas negara.
Dengan membangun konsensus di antara negara berkembang, Indonesia tidak hanya melindungi diri dari potensi lawfare, tetapi juga memperkuat tatanan hukum internasional yang lebih seimbang.
Karena jika hukum dapat menjadi senjata, maka diplomasi harus menjadi tameng, menjadi pedang yang melindungi setiap bangsa dari dominasi yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip keadilan universal. Indonesia harus siap, bukan hanya duduk di meja makan dunia, tetapi menentukan aturan mainnya. Ini adalah modal diplomasi untuk memperkuat visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
*) Ngasiman Djoyonegoro adalah analis intelijen, pertahanan dan keamanan, penulis buku Sketsa Diplomasi dan Pertahanan Nasional dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru