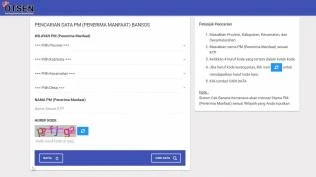Pernahkah Anda merasa sesak napas saat melihat unggahan kesuksesan teman di Instagram? Atau mungkin Anda sering mendengar kalimat, "Lihat anak tetangga, sudah punya rumah di usia muda," meluncur dari mulut orang tua sendiri? Jika ya, Anda tidak sendirian. Kita sedang hidup dalam sebuah epidemi budaya yang akut: budaya membanding-bandingkan (social comparison).
Ironisnya, banyak dari kita yang menjadi korban dari perilaku ini, namun secara sadar maupun tidak, kita juga menjadi pelaku yang meneruskan beban tersebut kepada generasi berikutnya. Kita terjebak dalam sebuah "lingkaran setan" yang melelahkan, di mana penderitaan dianggap sebagai standar, dan keaslian diri dianggap sebagai sebuah penyimpangan.
Warisan Trauma yang Menular
Membandingkan diri bukanlah sekadar kebiasaan buruk yang muncul tiba-tiba. Di Indonesia, hal ini telah menjadi warisan kultural yang diturunkan dari meja makan hingga ke ruang kelas. Sejak kecil, kita dididik dengan standar keberhasilan yang seragam: nilai akademik harus tinggi, masuk sekolah favorit, dan bekerja di perusahaan ternama dengan seragam mentereng.
Masalahnya, mereka yang pernah menjadi korban pembandingan ini—yang merasa hancur karena tidak bisa memenuhi ekspektasi—sering kali melakukan hal yang sama ketika mereka memiliki otoritas. Seorang kakak membandingkan adiknya dengan pencapaiannya sendiri, atau orang tua yang dulunya ditekan oleh kakek-nenek, kini melakukan hal serupa kepada anaknya dengan dalih "motivasi".
Padahal, ini bukanlah motivasi, melainkan transmisi trauma. Kita secara masif menyebarkan "virus" ketidakpuasan ini, membuat orang lain merasa tidak pernah cukup hanya karena mereka tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus sebelum melumat habis kesehatan mental generasi mendatang.
Logika Keberagaman: Mengapa Kita Diciptakan Berbeda?
Mari kita gunakan logika sederhana: Jika Tuhan menginginkan keseragaman, maka seluruh manusia akan memiliki sidik jari yang sama, minat yang serupa, dan jalan hidup yang kembar. Namun nyatanya, secara biologis dan spiritual, kita dirancang sebagai entitas yang unik.
Dalam perspektif apa pun, perbedaan adalah kunci dari harmoni. Jika semua orang menjadi dokter, siapa yang akan mendesain jembatan? Jika semua orang menjadi pengusaha, siapa yang akan menulis puisi yang menggetarkan jiwa? Keberagaman adalah cara alam semesta memastikan bahwa setiap celah kehidupan terisi. Kita diciptakan berbeda agar kita bisa saling melengkapi, bukan untuk saling mengalahkan dalam perlombaan yang garis finisnya ditentukan oleh standar orang lain. Ketika kita memaksa diri untuk menjadi "fotokopi" dari orang lain, kita sebenarnya sedang mengabaikan rencana-Nya. Sifat tidak bersyukur inilah yang menjadi akar dari penderitaan yang tak berkesudahan.
Dampak Psikologis dan Risiko Penyesalan
Hidup dalam bayang-bayang perbandingan hanya mengarah pada satu muara: penderitaan mental. Data dari Royal Society for Public Health (RSPH) dalam laporan "Status of Mind" menunjukkan bahwa media sosial memiliki kaitan erat dengan tingkat kecemasan, depresi, dan buruknya citra diri pada penggunanya. Hal ini dipicu oleh fenomena social comparison ekstrem, di mana kita membandingkan hidup kita yang "biasa saja" dengan cuplikan hidup orang lain yang telah dikurasi.
Sebuah studi dalam Journal of Social and Clinical Psychology mengungkapkan adanya hubungan kausal antara penggunaan media sosial dan penurunan kesejahteraan psikologis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa membatasi penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari secara signifikan mengurangi perasaan kesepian. Mengapa? Karena saat kita berhenti "mengintip" jendela hidup orang lain, kita mulai kembali memperhatikan pintu rumah kita sendiri.
Secara psikologis, stres kronis akibat perbandingan ini memicu rasa hampa. Kita kehilangan kemampuan menikmati proses karena fokus selalu tertuju pada pencapaian orang lain. Rumput tetangga memang tampak lebih hijau—namun kita lupa bertanya: apakah itu rumput asli, atau hanya ilusi digital yang dipoles filter?
Di akhir hayat, jarang ada orang menyesal karena tidak hidup seperti tetangganya. Bronnie Ware, seorang perawat paliatif dalam bukunya The Top Five Regrets of the Dying, mengungkapkan bahwa penyesalan nomor satu manusia adalah: "I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me." Penyesalan ini muncul ketika seseorang menyadari ia telah menghabiskan seluruh energinya untuk menjadi orang lain, hingga lupa mengenali siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Menjadi Diri Sendiri: Sebuah Tindakan Radikal
Banyak orang berpikir bahwa mengikuti arus adalah jalan yang paling aman. Padahal, mencoba menjadi orang lain adalah pekerjaan paling melelahkan di dunia. Anda harus memakai topeng setiap hari, menekan bakat asli, dan mengejar target yang tidak membuat hati Anda bergetar.
Hidup dengan talenta dan nilai personal adalah tindakan yang radikal. Mengapa? Karena pilihan ini hampir selalu disambut dengan pertanyaan sinis, kritik, bahkan cemoohan dari lingkungan yang terbiasa dengan keseragaman. Namun sejarah menunjukkan, kontribusi besar bagi dunia justru lahir dari mereka yang berdamai dengan dirinya sendiri. Seniman, inovator, hingga aktivis sosial tidak dikenal karena meniru, melainkan karena menekuni keunikan yang mereka miliki. Mereka tidak sibuk memenuhi ekspektasi semua orang—mereka sibuk bertumbuh.
Memutus Rantai: Dari Membandingkan ke Mensyukuri
Memutus lingkaran setan ini bukan perkara mudah, tetapi sangat mungkin. Langkah awalnya adalah berdamai dengan realitas diri sendiri—menerima bahwa setiap orang memiliki kemampuan, tempo, dan "musim" hidup yang berbeda. Berikut langkah nyata yang bisa dimulai hari ini:
Validasi Talenta Sendiri: Kenali apa yang membuat Anda merasa hidup. Jangan meremehkan bakat Anda hanya karena tidak sesuai dengan standar populer.
Kelola Konsumsi Media Sosial: Jika unggahan orang lain membuat Anda merasa tertinggal, berilah jarak. Fokus pada pertumbuhan internal, bukan pembuktian eksternal.
Berhenti Menjadi Pelaku: Jangan gunakan definisi sukses Anda untuk menghakimi hidup orang lain. Dukung anak, adik, pasangan, atau rekan kerja untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri—bukan replika dari siapa pun.
Rayakan Keunikan, Akhiri Perbandingan
Budaya membanding-bandingkan adalah penjara tanpa jeruji yang kita bangun bersama. Sudah saatnya kita merobohkannya. Setiap manusia adalah mahakarya yang unik. Menjadi orang lain adalah kemustahilan yang melelahkan, sementara menjadi diri sendiri sesuai karya Tuhan dalam hidup kita memerlukan keberanian dan tekad kuat.
Dunia tidak membutuhkan lebih banyak fotokopi. Dunia membutuhkan Anda—apa adanya, dengan jalan hidup yang Anda pilih sendiri. Mari berhenti saling melukai dengan perbandingan. Mari syukuri jalan masing-masing, dengan segala kerikil dan bunganya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa mirip hidup kita dengan orang lain, melainkan seberapa jujur kita menjalani hidup yang memang dititipkan kepada kita. Berdamailah dengan diri sendiri dan jalani hidup sesuai keinginan serta kemampuan Anda, agar tidak terjebak dalam penderitaan karena berusaha menjadi orang lain.