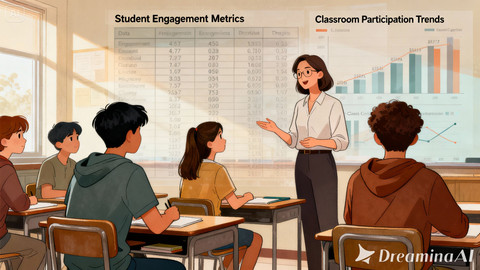Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia semakin didominasi oleh obsesi terhadap kepastian. Angka, skor, persentase, dan indeks diperlakukan sebagai penanda utama kebenaran ilmiah. Di ruang publik maupun ruang akademik, sesuatu dianggap sahih ketika dapat diukur, dihitung, dan ditampilkan dalam tabel atau grafik. Di balik kecenderungan ini, terdapat asumsi implisit bahwa yang tidak terukur secara ajeg atau kualitatif berarti tidak tergolong ilmiah.
Masalahnya, pendidikan bukan sekadar kumpulan variabel. Ia adalah ruang hidup manusia, tempat pengalaman, makna, relasi, dan konflik saling berkelindan. Ketika realitas yang kompleks ini dipaksa untuk selalu tampil dalam bentuk angka, yang sering terjadi bukanlah peningkatan objektivitas, melainkan penyempitan makna. Di sinilah praktik yang kerap mengatasnamakan penelitian deskriptif kuantitatif perlu ditinjau ulang secara epistemik.
Tulisan ini tidak bermaksud menolak metode kuantitatif. Yang dikritik adalah kecenderungan mengkuantifikasi fenomena kualitatif secara serampangan, lalu menyebutnya sebagai penelitian deskriptif kuantitatif, seolah angka dengan sendirinya menjamin kebenaran.
Pragmatisme dan Kebenaran yang BekerjaDalam filsafat pragmatisme, kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis dan melekat pada teori, melainkan sebagai sesuatu yang teruji dalam pengalaman. William James menyatakan bahwa kebenaran terjadi pada sebuah ide ketika ide itu bekerja dalam kehidupan nyata. John Dewey menekankan bahwa pengetahuan lahir dari proses penyelidikan terhadap masalah riil, bukan dari penerapan prosedur formal semata. Charles Sanders Peirce melalui prinsip pragmatic maxim menegaskan bahwa makna suatu konsep harus dilihat dari konsekuensi praktisnya.
Tiga tokoh ini sepakat dalam satu hal penting. Metode tidak boleh dipisahkan dari masalah yang dihadapi. Sebuah teori atau teknik hanya bermakna sejauh ia mampu membantu memahami dan memecahkan persoalan nyata. Dari sini, pragmatisme justru menolak kepastian semu yang diperoleh dari prosedur mekanis tanpa relevansi substantif.
Jika prinsip ini dibawa ke dalam penelitian pendidikan, maka pilihan metode bukan soal mengikuti template atau tren, melainkan soal kecocokan epistemik antara cara mengetahui dan objek yang diketahui.
Ketika Data Kehilangan MaknaDi banyak penelitian pendidikan, terutama yang berlabel deskriptif kuantitatif, dapat dijumpai praktik mengubah pengalaman, persepsi, atau interaksi manusia menjadi angka tanpa kerangka interpretasi yang memadai. Wawancara, refleksi siswa, atau dinamika kelas direduksi menjadi skor skala Likert, lalu disajikan sebagai persentase atau rerata. Angka-angka ini tampak rapi, tetapi sering kali tercerabut dari makna yang seharusnya mereka wakili.
Sebagai contoh, pengalaman belajar siswa yang penuh nuansa emosional dan sosial dapat dipadatkan menjadi skor kepuasan. Relasi guru dan murid yang kompleks disederhanakan menjadi indeks iklim kelas. Dalam proses ini, bukan hanya detail yang hilang, tetapi juga konteks yang memberi arti pada data tersebut.
Pragmatisme tidak membenarkan praktik seperti ini. Jika tujuan penelitian adalah memahami bagaimana siswa mengalami pembelajaran, maka metode yang menghapus pengalaman demi angka justru gagal secara epistemik. Angka tanpa interpretasi bukanlah kebenaran, melainkan ilusi kepastian.
Dampak bagi PendidikanKetika penelitian kehilangan kepekaan terhadap makna, kebijakan yang dibangun di atasnya pun berisiko menjadi tumpul. Data yang telah disederhanakan secara berlebihan mendorong lahirnya intervensi yang tidak responsif terhadap realitas peserta didik. Pendidikan lalu bergerak berdasarkan indikator, bukan berdasarkan pengalaman manusia yang hidup di dalamnya.
Sebaliknya, penelitian yang memadukan refleksi kualitatif dengan pertimbangan praktis yang cermat, sebagaimana ditekankan dalam pragmatisme, justru mampu menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan dan aplikatif. Ilmiah bukan berarti serba terukur, melainkan serba bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menjaga Etika KeilmuanDi tengah tekanan institusional untuk menghasilkan data yang rapi dan cepat, peneliti ditantang untuk menjaga integritas epistemik. Metode bukan sekadar alat teknis, melainkan pilihan moral tentang bagaimana manusia dan pengalamannya diperlakukan dalam proses ilmiah. Mengubah suara manusia menjadi angka tanpa makna adalah bentuk kekerasan simbolik yang sering tidak disadari.
Sebagai bagian dari komunitas akademik, peneliti memikul tanggung jawab yang jauh melampaui ruang kelas dan jurnal. Kesalahan dalam memahami realitas pendidikan dapat menjalar menjadi kebijakan yang membentuk generasi.
PenutupPragmatisme tidak pernah mengajarkan bahwa kebenaran itu mudah, instan, atau sekadar terukur. Ia justru menuntut keberanian untuk terus menguji, merevisi, dan menyesuaikan cara kita mengetahui dengan realitas yang dihadapi. Dalam penelitian pendidikan, ini berarti memilih metode bukan demi kepastian semu, tetapi demi pemahaman yang lebih jujur dan bermakna.