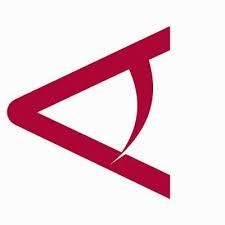Jakarta (ANTARA) - Yogyakarta kerap dirayakan sebagai ruang nostalgia tentang rindu, pulang, dan angkringan. Pengujung tahun selalu membawa keramaian tersendiri ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ketika wisatawan datang dan aktivitas pariwisata bergerak lebih padat daripada hari-hari biasa.
Di balik ritme aktivitas yang kian meningkat itu, persoalan upah dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak masih menjadi bagian dari keseharian banyak buruh di DIY.
Provinsi ini sering dipersepsikan sebagai wilayah dengan biaya hidup rendah. Faktanya, kebutuhan hidup terus meningkat, harga tanah melambung, sementara upah buruh bergerak jauh lebih lambat.
Ketimpangan inilah yang membuat persoalan upah minimum di DIY relevan untuk dibaca lebih dalam, bukan semata sebagai angka administratif tahunan, melainkan sebagai indikator kemampuan buruh mempertahankan standar hidup yang layak.
Pada 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan sebesar Rp2.417.495, naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengikuti formula nasional dengan nilai alpha 0,8 di tengah rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Secara nominal, kenaikan tersebut tampak cukup signifikan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah besaran upah tersebut memadai untuk menjawab kebutuhan hidup buruh di DIY?
Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DIY tahun 2025 menunjukkan angka Rp4.604.982. Nilai ini mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu pekerja untuk menopang kehidupan rumah tangganya secara layak. Artinya, terdapat selisih yang sangat lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang dihadapi buruh. Kenaikan upah, meskipun penting, belum sepenuhnya mampu menutup jurang tersebut.
Gambaran ini semakin jelas jika dikaitkan dengan data garis kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan DIY tahun 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar empat orang, satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah Rp2.505.452 per bulan.
Dengan UMP sebesar Rp2.417.495, seorang buruh lajang sekalipun, berada sangat dekat dengan batas minimum pemenuhan kebutuhan dasar, terlebih bagi buruh yang menjadi tulang punggung rumah tangga.
Perbandingan dengan daerah lain di Pulau Jawa memperlihatkan kontras yang mencolok. Kota Surabaya, misalnya, memiliki garis kemiskinan Rp775.579 per kapita per bulan atau sekitar Rp3.102.316 per rumah tangga. Namun, Upah Minimum Kota Surabaya pada 2026 mencapai Rp5.288.796. Dengan kebutuhan hidup dasar yang tidak terpaut jauh, buruh di Surabaya memiliki ruang fiskal yang jauh lebih longgar dibandingkan buruh di DIY.
Di Yogyakarta, upah minimum berada sangat dekat dengan batas bertahan hidup, sementara kota besar lain memberikan margin yang lebih aman bagi buruhnya.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan upah di DIY bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan juga berkaitan dengan struktur pasar kerja dan arah kebijakan yang diambil.
Dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, tekanan terhadap rumah tangga buruh di DIY menjadi lebih berat dibandingkan daerah lain dengan tingkat upah yang lebih longgar. Dalam konteks ini, kenaikan upah yang bersifat administratif berisiko tidak cukup menjawab tantangan kesejahteraan secara substantif.
Tanpa penyesuaian yang lebih sensitif terhadap dinamika biaya hidup, upah minimum dapat kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan dasar bagi rumah tangga pekerja.
Ironi ini semakin terasa ketika melihat posisi KHL DIY secara nasional. Nilai KHL DIY yang menyentuh Rp4,6 juta lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten (Rp4,3 juta), Jawa Barat (Rp4,2 juta), Jawa Tengah (Rp3,6 juta), dan Jawa Timur (Rp3,6 juta). Dengan kata lain, biaya hidup di DIY mendekati wilayah metropolitan, tetapi tingkat upahnya justru berada di level yang jauh lebih rendah.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi DIY. Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY triwulan III-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya menyumbang 12,93 persen terhadap perekonomian daerah. Pariwisata menjadi penggerak utama, menarik jutaan wisatawan setiap tahun dan menghidupkan hotel, restoran, serta jasa transportasi.
Di sisi lain, DIY juga menjadi tujuan pendidikan dan migrasi kerja dari berbagai daerah. Ratusan ribu mahasiswa dan pendatang baru menciptakan pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dalam kondisi ini, daya tawar buruh cenderung melemah. Ketika tenaga kerja tersedia dalam jumlah besar, tekanan untuk menahan upah menjadi lebih kuat, meskipun biaya hidup terus meningkat.
Situasi ini menempatkan banyak rumah tangga buruh dalam kondisi rentan. Dengan pendapatan sekitar Rp2,4 juta per bulan, ruang untuk menabung hampir tidak ada. Pengeluaran difokuskan untuk kebutuhan harian, sementara kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak, dana darurat, atau perlindungan kesehatan, sering kali harus dikorbankan. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi material, tetapi juga pada rasa aman dan stabilitas sosial rumah tangga buruh.
Dalam jangka panjang, tantangan ini berpotensi membentuk persoalan struktural yang lebih luas. Harga tanah dan rumah di DIY terus meningkat, sementara kemampuan buruh untuk mengakses kepemilikan rumah sangat terbatas. Dengan tingkat upah saat ini, akses terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi hampir mustahil bagi buruh muda yang tidak memiliki dukungan aset keluarga. Ketimpangan kepemilikan aset pun berisiko semakin menganga.
Merespons kondisi ini, ruang perbaikan kebijakan masih terbuka. Pertama, penetapan upah minimum ke depan dapat secara bertahap lebih responsif terhadap KHL. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengusulkan penyesuaian agar upah minimum bergerak menuju 70–80 persen KHL dalam beberapa tahun ke depan, dengan target jangka menengah mencapai 100 persen, tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Kedua, pendekatan sektoral dalam kebijakan pengupahan layak dipertimbangkan. Tidak semua sektor memiliki kapasitas yang sama. Sektor pariwisata premium, misalnya, memiliki margin keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan UMKM. Diferensiasi kebijakan upah dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan buruh dan keberlanjutan pelaku usaha kecil.
Ketiga, persoalan mendasar di DIY adalah kelebihan pasokan tenaga kerja. Investasi pada pelatihan keterampilan, ekonomi digital, kewirausahaan, dan manajemen pariwisata bernilai tambah tinggi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang lebih baik. Upaya ini bukan solusi instan, tetapi penting untuk memperkuat struktur pasar kerja dalam jangka panjang.
Terakhir, pengawasan dan transparansi tetap menjadi elemen penting. Kepatuhan terhadap upah minimum perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan yang konsisten, disertai insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi proporsional bagi pelanggaran. Pendekatan ini dapat menjaga iklim usaha, sekaligus melindungi hak dasar buruh.
Yogyakarta akan selalu memiliki daya tarik budaya dan sosial yang membuat orang ingin kembali. Hanya saja, keberlanjutan daya tarik tersebut sangat bergantung pada kesejahteraan mereka yang menjaga dan menggerakkan ekonomi sehari-hari. Ketika buruh memperoleh upah yang lebih layak, daya beli meningkat, usaha lokal bergerak lebih dinamis, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.
Pada akhirnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari ramainya wisatawan atau tingginya PDRB, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan secara nyata oleh rumah tangga buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
*) Arvia Dwi Royani dan Lili Retnosari adalah statistisi BPS RI
Di balik ritme aktivitas yang kian meningkat itu, persoalan upah dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup layak masih menjadi bagian dari keseharian banyak buruh di DIY.
Provinsi ini sering dipersepsikan sebagai wilayah dengan biaya hidup rendah. Faktanya, kebutuhan hidup terus meningkat, harga tanah melambung, sementara upah buruh bergerak jauh lebih lambat.
Ketimpangan inilah yang membuat persoalan upah minimum di DIY relevan untuk dibaca lebih dalam, bukan semata sebagai angka administratif tahunan, melainkan sebagai indikator kemampuan buruh mempertahankan standar hidup yang layak.
Pada 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY ditetapkan sebesar Rp2.417.495, naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengikuti formula nasional dengan nilai alpha 0,8 di tengah rentang 0,5 hingga 0,9 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Secara nominal, kenaikan tersebut tampak cukup signifikan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah besaran upah tersebut memadai untuk menjawab kebutuhan hidup buruh di DIY?
Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DIY tahun 2025 menunjukkan angka Rp4.604.982. Nilai ini mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu pekerja untuk menopang kehidupan rumah tangganya secara layak. Artinya, terdapat selisih yang sangat lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang dihadapi buruh. Kenaikan upah, meskipun penting, belum sepenuhnya mampu menutup jurang tersebut.
Gambaran ini semakin jelas jika dikaitkan dengan data garis kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan DIY tahun 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar empat orang, satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah Rp2.505.452 per bulan.
Dengan UMP sebesar Rp2.417.495, seorang buruh lajang sekalipun, berada sangat dekat dengan batas minimum pemenuhan kebutuhan dasar, terlebih bagi buruh yang menjadi tulang punggung rumah tangga.
Perbandingan dengan daerah lain di Pulau Jawa memperlihatkan kontras yang mencolok. Kota Surabaya, misalnya, memiliki garis kemiskinan Rp775.579 per kapita per bulan atau sekitar Rp3.102.316 per rumah tangga. Namun, Upah Minimum Kota Surabaya pada 2026 mencapai Rp5.288.796. Dengan kebutuhan hidup dasar yang tidak terpaut jauh, buruh di Surabaya memiliki ruang fiskal yang jauh lebih longgar dibandingkan buruh di DIY.
Di Yogyakarta, upah minimum berada sangat dekat dengan batas bertahan hidup, sementara kota besar lain memberikan margin yang lebih aman bagi buruhnya.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan upah di DIY bukan semata soal kemampuan fiskal daerah, melainkan juga berkaitan dengan struktur pasar kerja dan arah kebijakan yang diambil.
Dengan tingkat biaya hidup yang relatif tinggi, tekanan terhadap rumah tangga buruh di DIY menjadi lebih berat dibandingkan daerah lain dengan tingkat upah yang lebih longgar. Dalam konteks ini, kenaikan upah yang bersifat administratif berisiko tidak cukup menjawab tantangan kesejahteraan secara substantif.
Tanpa penyesuaian yang lebih sensitif terhadap dinamika biaya hidup, upah minimum dapat kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan dasar bagi rumah tangga pekerja.
Ironi ini semakin terasa ketika melihat posisi KHL DIY secara nasional. Nilai KHL DIY yang menyentuh Rp4,6 juta lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten (Rp4,3 juta), Jawa Barat (Rp4,2 juta), Jawa Tengah (Rp3,6 juta), dan Jawa Timur (Rp3,6 juta). Dengan kata lain, biaya hidup di DIY mendekati wilayah metropolitan, tetapi tingkat upahnya justru berada di level yang jauh lebih rendah.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi DIY. Berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY triwulan III-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya menyumbang 12,93 persen terhadap perekonomian daerah. Pariwisata menjadi penggerak utama, menarik jutaan wisatawan setiap tahun dan menghidupkan hotel, restoran, serta jasa transportasi.
Di sisi lain, DIY juga menjadi tujuan pendidikan dan migrasi kerja dari berbagai daerah. Ratusan ribu mahasiswa dan pendatang baru menciptakan pasokan tenaga kerja yang melimpah. Dalam kondisi ini, daya tawar buruh cenderung melemah. Ketika tenaga kerja tersedia dalam jumlah besar, tekanan untuk menahan upah menjadi lebih kuat, meskipun biaya hidup terus meningkat.
Situasi ini menempatkan banyak rumah tangga buruh dalam kondisi rentan. Dengan pendapatan sekitar Rp2,4 juta per bulan, ruang untuk menabung hampir tidak ada. Pengeluaran difokuskan untuk kebutuhan harian, sementara kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan anak, dana darurat, atau perlindungan kesehatan, sering kali harus dikorbankan. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi material, tetapi juga pada rasa aman dan stabilitas sosial rumah tangga buruh.
Dalam jangka panjang, tantangan ini berpotensi membentuk persoalan struktural yang lebih luas. Harga tanah dan rumah di DIY terus meningkat, sementara kemampuan buruh untuk mengakses kepemilikan rumah sangat terbatas. Dengan tingkat upah saat ini, akses terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi hampir mustahil bagi buruh muda yang tidak memiliki dukungan aset keluarga. Ketimpangan kepemilikan aset pun berisiko semakin menganga.
Merespons kondisi ini, ruang perbaikan kebijakan masih terbuka. Pertama, penetapan upah minimum ke depan dapat secara bertahap lebih responsif terhadap KHL. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengusulkan penyesuaian agar upah minimum bergerak menuju 70–80 persen KHL dalam beberapa tahun ke depan, dengan target jangka menengah mencapai 100 persen, tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Kedua, pendekatan sektoral dalam kebijakan pengupahan layak dipertimbangkan. Tidak semua sektor memiliki kapasitas yang sama. Sektor pariwisata premium, misalnya, memiliki margin keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan UMKM. Diferensiasi kebijakan upah dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan buruh dan keberlanjutan pelaku usaha kecil.
Ketiga, persoalan mendasar di DIY adalah kelebihan pasokan tenaga kerja. Investasi pada pelatihan keterampilan, ekonomi digital, kewirausahaan, dan manajemen pariwisata bernilai tambah tinggi dapat membantu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang lebih baik. Upaya ini bukan solusi instan, tetapi penting untuk memperkuat struktur pasar kerja dalam jangka panjang.
Terakhir, pengawasan dan transparansi tetap menjadi elemen penting. Kepatuhan terhadap upah minimum perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan yang konsisten, disertai insentif bagi perusahaan yang patuh dan sanksi proporsional bagi pelanggaran. Pendekatan ini dapat menjaga iklim usaha, sekaligus melindungi hak dasar buruh.
Yogyakarta akan selalu memiliki daya tarik budaya dan sosial yang membuat orang ingin kembali. Hanya saja, keberlanjutan daya tarik tersebut sangat bergantung pada kesejahteraan mereka yang menjaga dan menggerakkan ekonomi sehari-hari. Ketika buruh memperoleh upah yang lebih layak, daya beli meningkat, usaha lokal bergerak lebih dinamis, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.
Pada akhirnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari ramainya wisatawan atau tingginya PDRB, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan itu dirasakan secara nyata oleh rumah tangga buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
*) Arvia Dwi Royani dan Lili Retnosari adalah statistisi BPS RI