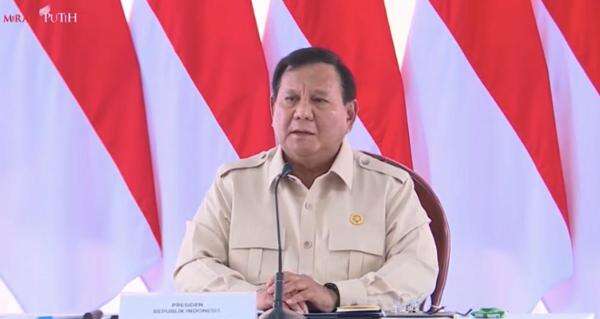SEPANJANG 2025, Sumatra Utara dihantam rangkaian bencana ekologis, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kerusakan wilayah pesisir. Bencana tersebut menelan korban jiwa, merusak permukiman warga, serta memutus sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah. Di balik peristiwa-peristiwa itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai terdapat persoalan struktural yang selama ini diabaikan Negara.
Melalui agenda Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Walhi Sumut mengungkap bahwa bencana yang berulang tidak semata dipicu oleh faktor alam dan krisis iklim global, melainkan juga oleh kebijakan pembangunan yang membuka ruang luas bagi perusakan lingkungan serta penegakan hukum yang gagal melindungi ekosistem dan masyarakat.
Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Utara, Rianda Purba mengatakan bahwa perubahan iklim memang meningkatkan intensitas cuaca ekstrem. Namun di Sumatra Utara, dampaknya menjadi jauh lebih parah karena hutan dan ekosistem penting yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan justru terus dihancurkan.
“Banjir dan longsor yang terjadi bukan hanya soal hujan lebat. Ketika hutan di hulu hilang, mangrove di pesisir rusak, dan daerah tangkapan air berubah fungsi, maka bencana tinggal menunggu waktu. Ini bukan takdir, tetapi hasil dari kebijakan yang salah arah,” kata Rianda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1).
Walhi Sumut menempatkan Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli) sebagai contoh paling nyata keterkaitan antara deforestasi dan bencana ekologis. Kawasan ini merupakan daerah hulu bagi sungai-sungai besar di Sumatera Utara, berfungsi sebagai daerah tangkapan air, serta habitat terakhir Orangutan Tapanuli yang tersisa sekitar 700 individu.
Meski telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup, dalam lima tahun terakhir Walhi Sumut mencatat lebih dari 10 ribu hektare tutupan hutan di Batang Toru hilang akibat aktivitas industri tambang emas, pembangkit listrik, kehutanan, dan perkebunan.
Kerusakan tersebut berdampak langsung pada bencana banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Tapanuli Raya pada November 2025. Saat bencana terjadi, sungai-sungai dipenuhi ribuan kubik kayu gelondongan dan lumpur, yang menyapu permukiman warga dan lahan pertanian.
“Ketika hutan di hulu digunduli, air tidak lagi tertahan. Yang datang ke hilir bukan hanya air, tetapi juga kayu, lumpur, dan kematian,” beber Rianda.
Selain hutan daratan, Walhi Sumut juga mencatat krisis serius pada hutan mangrove di wilayah pesisir Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat. Sepanjang 2025, sekitar 200 hektare hutan mangrove dirusak dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit dan tambak.
Salah satu kasus menonjol terjadi di wilayah kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah, yang telah mengantongi izin perhutanan sosial dari pemerintah. Alih-alih dilindungi, masyarakat justru menghadapi perambahan, intimidasi, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat dalam upaya perampasan wilayah kelola.
Padahal, mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami pesisir dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim. Kerusakan mangrove, menurut Walhi Sumut, akan memperbesar risiko bencana di wilayah pesisir dan mengancam mata pencaharian nelayan.
Walhi Sumut juga mencatat sedikitnya empat kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat, pejuang lingkungan, dan warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sepanjang 2025. Bahkan, upaya penertiban kawasan hutan oleh pejabat daerah pun tidak luput dari proses hukum yang dinilai janggal.
Melalui CATAHU 2025, Walhi Sumut menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar dokumentasi tahunan, melainkan peringatan keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak pada perlindungan ekosistem dan masyarakat, Sumatera Utara akan terus berada dalam lingkaran bencana ekologis yang berulang.
Untuk itu, Walhi Sumut mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana ekologis di Sumatera sebagai bencana nasional, menghentikan laju deforestasi melalui moratorium dan pencabutan izin, serta membersihkan aparat dan institusi Negara dari praktik mafia ekologis.
“Jika negara terus memandang hutan hanya sebagai komoditas dan hukum sebagai alat kekuasaan, maka korban bencana akan terus bertambah. Catatan akhir tahun ini adalah alarm yang tidak boleh lagi diabaikan,” kata Rianda.
Ahli Kebencanaan dari Yayasan Pusaka, Marjoko, menambahkan bahwa akar persoalan krisis ekologis di Sumatera Utara terletak pada mandulnya penegakan hukum lingkungan. Negara dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap korporasi perusak lingkungan, sementara masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya justru kerap berhadapan dengan kriminalisasi.
“Bencana ekologis ini lahir dari ketimpangan relasi kuasa. Hukum tajam ke masyarakat, tetapi tumpul ke perusahaan besar. Selama kondisi ini dibiarkan, bencana akan terus diproduksi oleh kebijakan negara sendiri,” kata Marjoko.